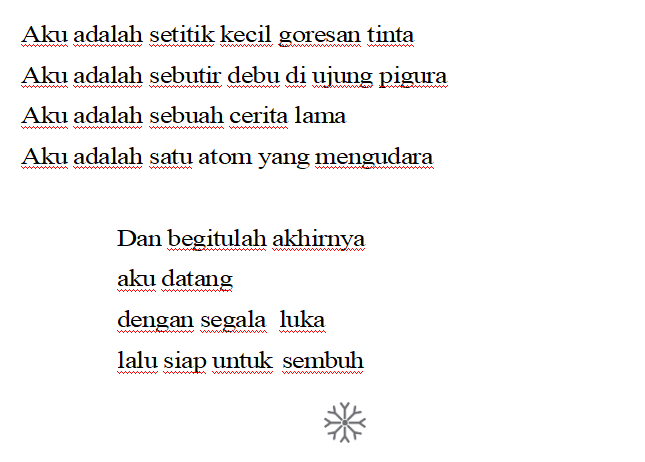
“Aku punya anak, namanya Finn,” ucap Nyonya Emma memecah keheningan.
Aku menatapnya. “Oh, iya? Berapa umurnya?” tanyaku.
Wanita paruh baya itu menjawab, “Delapan belas tahun, sama sepertimu. Tapi, dia lain.”
Aku memicingkan mata. “Lain bagaimana?” “Sindrom Down,” jawabnya pelan.
Dalam hati, aku terkejut. Dua kata itu tidak begitu asing saat didengar oleh telingaku. Aku juga sempat mempelajarinya dalam pelajaran Biologi pada bab mu- tasi genetik. Aku tahu, itu bukanlah pertanda yang bagus. Namun, kucoba untuk bersikap biasa saja. “Aku bisa berteman dengannya, kok,” kataku untuk menghibur.
“Benarkah?”
Aku mengangguk. “Ya, tentu saja. Mengapa tidak?” “Dia cukup sensitif saat melihat wajah baru. Tapi,
kelebihannya, dia lebih peka pada keadaan di sekitarnya dibanding penderita sindrom Down lainnya. Setidaknya, itu kata dokter.”
“Dia akan baik-baik saja,” ucapku yakin.
Beliau tersenyum. “Syukurlah kamu tidak berpikir jelek tentang hal itu. Beberapa orang memandang anakku itu dengan pandangan jelek.”
“Aku cukup paham mengapa Anda berpikir seperti itu. Tapi, aku bukanlah orang awam mengenai hal itu. Setidaknya, aku pernah mempelajarinya sekali dalam sejarah hidupku.”
“Aku harap begitu, Sayang,” balasnya parau.
Aku tersenyum kecil. “Anda sudah melakukan yang terbaik, Nyonya Emma. Jangan khawatirkan apa pun.” “Dari ucapanmu barusan, sepertinya kamu pandai menguatkan orang lain, Alyssa. Kuharap, kamu bisa menguatkan dirimu juga,” harapnya.
Aku tertegun, lalu melemparkan pandangan ke jendela. Lagu sedih lalu terputar dalam benakku. Kami membiarkan diri masing-masing tenggelam dalam lamunan. Kuharap, kami adalah sepasang wanita yang berteman dengan baik seperti dulu ibuku dan Nyonya Emma berteman baik.
Kami menempuh 5 jam perjalanan menggunakan kereta. Selama perjalanan menuju Little Switzerland, kami disuguhi pemandangan yang menakjubkan tidak pernah kulihat sebelumnya. Hamparan rumput serta deretan pohon pinus yang memagar di pinggir taman nasional membuat mataku kembali membaik setelah berhari-hari menangis seperti bocah.
“Kukira, Little Switzerland yang dimaksud adalah Swiss sungguhan di Eropa,” keluhku tiba-tiba.
Nyonya Emma tertawa lucu. “Bukan, bukan. Itu adalah tempat wisata yang selalu ramai pada musim dingin. Carolina Utara punya Swiss mini. Tempatnya menyerupai Swiss sungguhan. Percayalah padaku. Di sana ada rumah ibumu yang akan kamu tinggali,” katanya.
Aku menatapnya risau. “Aku tidak pernah tahu Ibu punya rumah di sana. Dia tidak pernah memberitahuku.” “Ya, ibumu punya rumah di sana. Seperti rumah kenangan, lah,” sahutnya sambil melemparkan senyum. Aku tidak membalasnya. “Seiring berjalannya waktu, semuanya akan membuka mata, hati, dan pikiranmu, Alyssa.”
Aku menghela napas panjang. “Aku telah mening- galkan segalanya. Kalau aku tak dapatkan apa-apa di tempat yang dimaksud, aku akan menyalahkanmu, Nyonya Emma. Aku tidak bercanda.”
Dia membalasku dengan senyuman lagi. Kutatap wanita berusia 50 tahunan itu. Pada wajahnya sudah terdapat banyak kerutan. Sorot matanya tegas, tetapi sayu. Keletihan sesekali memancar dari auranya. Syal kunonya menandakan dia datang dari masa lalu. Keraguan mulai merebak di dalam hati. Aku menatap- nya penuh selidik. Namun, dia hanya tersenyum lagi dan lagi, berusaha menguatkanku. Ah, perasaanku tak menentu.
Menjadi sebatang kara membuatku memberontak pada dunia. Berkali-kali, aku menyalahkan Tuhan atas takdirku. Tapi, setelahnya, hatiku terasa ditampar oleh tangan tak kasatmata. Aku hanya menangis kesakitan dibuatnya. Aku menerawang pada birunya langit dari balik jendela kereta, membisikkan segala harapan, seolah-olah Tuhan jauh dariku. Ah, hatiku kembali ditampar. Diam-diam, aku menangis lagi di balik syalku, lalu membuang pandangan ke jendela kereta.
Bagiku, mengingat-ingat kenangan bagaikan me- meluk kaktus. Semakin erat akan semakin sakit. Namun, aku tidak berusaha menghindarinya. Aku menikmati kepedihanku dengan pemahaman yang semakin sulit.
Ah, entahlah. Pikiranku kosong. Aku tidak mampu berbuat apa-apa selain mengikuti alurnya saja. Aku tidak berdaya atas kuasa Tuhan. Aku hanya ingin memejamkan mata sejenak supaya lupa akan segalanya. Aku terus berbicara kepada diriku sendiri, bahkan di alam mimpi sekalipun.
***
Setibanya di Stasiun Marion, kami turun. Nyonya Emma dan aku membawa barang-barang bawaan yang cukup banyak. Stasiunnya tidak begitu besar, tetapi ditata sedemikian apik dengan nuansa Eropa. Di tempat pen- jemput, seseorang mengacungkan kertas karton dengan nama “Emma Ann Wilson” berwarna merah menyala.
“Itu sopirku. Ayo, Sayang!” kata Nyonya Emma sambil menunjuk orang itu.
Aku mengikuti langkahnya di belakang. Kami ke- luar dari pintu masuk stasiun. Orang suruhan tersebut mengambil alih barang bawaan kami yang cukup banyak dan membawanya ke mobil Ford dengan bak terbuka. Aku dipersilakan duduk di kursi belakang, sementara Nyonya Emma dan sopirnya di depan. Mobil pun berjalan membawa kami ke dataran yang lebih tinggi lagi.
Aku belum pernah ke Marion sepanjang hidupku. Selama perjalanan, kami disuguhi pemandangan kota yang tak terlalu mewah. Semakin lama, kurasakan jalanan semakin menanjak. Sepasang telingaku mulai terasa tersumbat oleh tekanan udara yang tak stabil. Beberapa kilo lagi menuju Little Switzerland. Peman- dangan kota mulai tergantikan dengan rumah hunian maupun vila. Pohon-pohon mahoni dan cemara yang warna hijaunya mulai memudar membuat semarak pemandangan.
Kurang dari 1 jam kemudian, plang kayu besar dengan tulisan “Welcome to Little Switzerland” me- nyambut kehadiran kami. Sepanjang mata memandang, hanya terlihat perladangan sayur dan buah. Beberapa petani tradisional tampak melambaikan tangan kepada Nyonya Emma. Peternakan khas Eropa menjadi pe- mandangan berikutnya yang mengesankan. Apalagi, ditambah tumpukan jerami kering.
Semakin kami naik, mulai terlihat jajaran penginapan mewah dengan jacuzzi outdoor. Bunga-bunga menghiasi pintu dan jendelanya. Pagar kayu sederhana yang sedari dulu tidak aku hiraukan, kini berhasil membuatku terpana. Setiap inci detail yang terlihat menambah keyakinanku bahwa kami sekarang sudah berada di belahan dunia yang lain, bukan di Carolina Utara.
Sebuah toko bunga yang penuh dengan pembeli mencuri perhatianku. Di seberangnya terdapat tempat belanja grosir yang tampaknya akan sering dikunjungi olehku. Kulihat sisi lain yang jauh di sana, sebuah tebing menjulang tinggi dengan lumut yang melapisi beberapa bagiannya.
Jantungku semakin berdebar.
Jalanan mulai menyempit dan mobil yang kami tumpangi berhenti di depan sebuah motel sederhana bergaya Eropa. Tidak ketinggalan, dengan pot-pot bunga yang menjuntai dari balkon menambah daya tarik motel tersebut. Motel itu bernama “Ann Inn”. Kami turun dari mobil. Beberapa orang menyambut kedatangan kami di depan motel itu.
“Bagaimana, Alyssa? Kamu suka?” tanya Nyonya Emma sambil tersenyum.
Aku tersenyum kecil. “Ini seperti di Swiss.”
“Ini motel milikku yang dikelola langsung olehku. Rumahku ada di atas. Ayo! Alex, tolong bawakan koper- koper itu, ya!” suruhnya kepada seseorang.
Kami beriringan menaiki tangga batu yang me- nanjak. Aku menoleh ke belakang. Oh, ya, ampun. Pemandangan bagus sekali tampak dari atas sini! Warna hijau di mana-mana. Langit biru yang bersih semakin membuatku lega. Ini sulit dipercaya!
Tak lama kemudian, kami tiba di depan rumah Nyonya Emma. Rumahnya dicat putih dengan dua lantai yang tidak terlalu besar. Halamannya rapi de- ngan macam-macam bunga tumbuh subur di depannya. Ada kolam ikan kecil dengan tanaman perdu di sekelilingnya.
“Nah, Alyssa. Ini rumahku. Tapi, kamu akan tinggal di sana,” ucapnya sambil menunjuk sebuah rumah di puncak yang tidak jauh dari tempat kami berpijak.
Aku menoleh ke arah yang dimaksud. Sebuah rumah dua tingkat berwarna putih dengan atap berwarna maroon berdiri kokoh seolah melambai-lambai ke arahku.