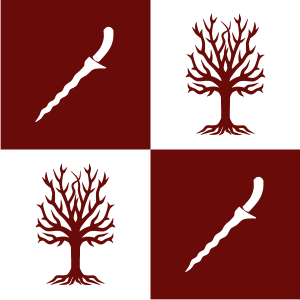
Pemain terakhir dalam Perang Empat Bajingan datang dari Putra-Putri Laut. Seorang pria bertubuh kecil yang selalu mengenakan topeng orang tertawa. Sebab memiliki perangai aneh dan asal-usul tak jelas, dia dibenci lawan maupun kawan. Nama aslinya Jayagiri Bunilayar, tapi mereka lebih mengenalnya dengan sebutan Alitdaksa.—Perang Empat Bajingan, Safia al'Nukhar
ALITDAKSA MENYEBUT benteng ini Simpang Tilu—tiga persimpangan—karena dibangun di antara tiga aliran sungai. Dia tak tahu nama aslinya. Dia juga tak tahu siapa pemilik awalnya. Satu-satunya identitas mereka yang terkuak hanyalah dua panji-panji: satu terbuat dari kulit domba, dipotong hingga membentuk tali berujung bulan sabit; satu berupa sehelai kain hitam dengan lingkaran merah di tengahnya.
Ada banyak menara di sana, tapi cuma satu yang Alitdaksa sukai—kalau memang makhluk itu masih bisa menyukai sesuatu. Menara Debur, dia memanggilnya. Dibangun di batu karang keras yang menjorok jauh ke sungai, dengan arus air berdebur di bawahnya.
Alitdaksa berdiri di balkon luar. Langit sedang cerah ketika itu. Bintang berhamburan di langit, gemerlap memenuhi sepenjuru cakrawala. Sebentar, Alitdaksa mengernyit. Tak ada bulan. Ini siang hari, duh. Bukan malam. Dalam pelayaran besarnya, Alitdaksa sudah meninggalkan mentari satu tahun di belakangnya. Meski begitu, masih sulit terbiasa dengan dunia macam itu.
Tangan kanan Alitdaksa—Panaraban—berdiri di sampingnya, tubuh menjulang sampai dua jengkal bedanya. Bukan sebab pria itu tinggi, tapi lebih karena Alitdaksa pendek—cebol bila dibandingkan dengan kebanyakan lelaki dan sebagian perempuan.
"Indah, bukan?" tanya Alitdaksa. Panaraban mengangguk. Kedua pria itu layaknya siang dan malam. Paraban tinggi, bertubuh kekar, dengan otot tebal yang tercetak layaknya dinding batu. Alitdaksa sendiri pendek, bertubuh kurus, dengan sekujur badan yang dibalut perban sutra. Topeng kayu menutup wajahnya, diukir dalam bentuk orang terbahak—wajah Pohaci Nangling. "Jarang kau bisa lihat pemandangan macam ini."
"Patik, Radén Menggung. Langitnya sedang cerah."
"Kau melantur apa, Panaraban. Langit dengkulmu. Yang aku maksud itu hutannya."
"Euh .... hutan?" Panaraban diam sejenak. "Hutannya ... sedang terbakar ... Radén Menggung."
"Iya. Lihat, kok. Kan, aku sendiri yang suruh bakar."
Dari sana, Alitdaksa dapat melihat lidah-lidah api raksasa menjilati hutan di bawah dengan rakus. Asap membumbung, bunga bara berhamburan. Hutan edan, pikirnya. Hutan dengan pepohonan yang mampu tumbuh di kegelapan malam, tanpa adanya sinar mentari. Dan penghuni negerinya tak kalah edan.
"Itu ... indah, Radén Menggung?" ulang Panaraban. Dari nada suaranya yang penuh kekhawatiran, kelihatannya dia mulai mengira kalau majikannya akhirnya mulai gila. Dia tidak tahu kalau majikannya memang sudah gila.
"Luar biasa. Macam ... macam ... macam neraka." Alitdaksa diam sejenak, tangan kurus mengusap mulut topeng. "Penasaran apa neraka memang bakal macam ini. Bagaimana menurutmu, Panaraban?"
"Memangnya ... kenapa, Radén?"
"Kenapa, Panaraban? Hah! Aku cuma penasaran saja. Apa tak boleh aku penasaran dengan tempat yang bakal aku tuju, Panaraban?"
"Radén ingin pergi ke Neraka?"
"Pertanyaan manis, Panaraban, yang jawabannya tak kalah manis juga."
"'Iya'?"
"Dengkulmu!" Alitdaksa terbatuk. Huh. Kalem, Alitdaksa. Tak ada gunanya orang lemah emosian. Marahmu tidak menakutkan, soalnya. "Tapi aku sudah kehilangan Radén Pangeran Hulugalah. Si dedemit bangsat main kejauhan, dan sekarang entah ngebangkai di mana pula. Berdasarkan pengamatan soal kepopuleranku ... tentunya tumenggung yang lain bakal kira aku yang bunuh dia. Macam aku yang beneran bisa bunuh itu setan weduk saja." Alitdaksa mendengus. "Atau menurutmu aku bakal masuk surga, Panaraban?"
"Surga atau neraka, sahaya tetap bakal menemani Radén."
"Oh. Macam biasa, kau kelewat baik denganku. Apa otakmu baik-baik saja? Tak ingat pernah pasang susuk atau kirim pelet pada dirimu," komentar Alitdaksa sinis, tapi di balik topeng, mulutnya tersenyum. Senyum miring, tapi tetap saja senyum. "Kalau waktunya sudah tiba, kau mesti fitnah aku, Panaraban."
"Fitnah, Radén?"
"Oh. Pokoknya salahkan saja semuanya padaku. Jadi kreatif sedikit, bisa, kan? Bilang kalau aku diam-diam menantang si dedemit Hulugalah duel dan menonjoknya sampai mental ke langit."
Panaraban penatap tubuh majikannya yang kecil, kurus, lagi penyakitan.
"Oh, baiklah, Panaraban. Bilang saja kalau aku membekap wajahnya pakai bantal waktu dia tidur. Tambahkan sedikit detail juga. Bilang kalau aku menjerit-jerit histeris waktu melakukannya. Dan aku kencing di celana saking takutnya. Kujamin mereka bakal percaya." Alitdaksa terkekeh, lalu terbatuk, lalu terkekeh lagi, lalu terbatuk lagi, lalu mengumpat. "Yang penting jangan sampai kau ikut ke neraka denganku. Para gadis di seluruh kapal bakal mengutukku kalau kau mati gara-gara aku."
Dan Alitdaksa tidak melebih-lebihkan. Para gadis ribut ketika Paraban lewat, menjerit ketika melihatnya terseyum, lalu pingsan ketika si pria bertelanjang. Huh. Sebentar. Kenapa juga aku iri? Menurut pengalaman, para gadis juga ribut ketika Alitdaksa lewat, menjerit ketika melihatnya tersenyum, lalu pingsan ketika dia bertelanjang. Bedanya, mereka ribut karena ingin kabur dari bau tubuhnya yang busuk, menjerit karena takut lihat giginya yang ompong, dan pingsan karena teror tiada hingga dari penampilan aslinya.
"Jangan bilang begitu, Radén." Panaraban mengernyit ke arah langit. "Lagi pula, mungkin kita memang sudah ada di neraka."
Di sisi lain, di seberang Poros Dunia, terdapat negeri-negeri manusia. Putra-Putri Laut datang dari sana. Tempat yang aneh, diisi oleh orang-orang aneh. Alitdaksa pernah bertemu dengan kaum Separuh Dewa, dengan tubuh sejangkung tiang, kulit putih pucat, rambut emas, serta mata dan darah sewarna laut dalam. Ada pula ras Asali, dengan tubuh pendek, kulit kuning, mata hitam, dan menyembah langit. Kendati begitu, Alitdaksa tak pernah melihat sesuatu yang macam ini.
Musuh-musuhnya, para penghuni sebelumnya dari benteng yang kini dihuni pasukan armada Jala Layung, memiliki rupa yang berbeda-beda. Mereka ras campuran. Beberapa bermata sipit, beberapa berambut merah, beberapa pendek, beberapa jangkung, dan mereka menjerit dalam bahasa yang berbeda kala dibantai. Mereka bukan dari bangsa yang sama, tapi bersatu di bawah satu panji. Itu sesuatu yang tak pernah Alitdaksa lihat di Dunia Seberang. Meski begitu, mereka tetap punya satu kesamaan: darah mereka hitam dan masam.
Darah yang tak menyembur, kental bagai getah. Baunya busuk, dan kala disentuh, kulit terasa pedih bak dikupas ari-arinya. Sudah nyaris seperempat musim Armada Jala Layung menaklukkan benteng ini, tapi tubuh-tubuh itu tak kunjung membusuk, tidak pula dimakan hewan-hewan. Jayagiri memerintahkan agar mayat-mayat tersebut ditumpuk dan dibakar, dan api pun melahap mereka dengan rakus seolah tengah melahap lilin.
"Siang tak pernah datang," ungkap Panaraban geram. "Hanya malam. Negeri ini sudah mati, Radén."
"Kau merasa dingin, Panaraban?" Alitdaksa mengusap pelan perutnya yang terbaluk perban. Bekas borok, bisul, dan ruam bergerinjal kala disentuh. "Aku benci udara hangat. Buat gatalku kambuh."
Panaraban mengernyit, menyadari siratan dalam perkataan Alitdaksa. "Udara memang dingin ...."
"... tapi tak cukup dingin. Tidak macam waktu kita berlayar, eh?" Alitdaksa masih ingat kejadian itu. Bulan-bulan dalam deraan angin dingin yang menusuk dan membekukan darah. "Utamanya ketika bulan muncul. Malah terasa nyaris panas. Macam matahari. Tumbuhan di sini subur, dan hewan-hewan hidup berlimpah—walau dalam bentuk yang sedikit ... edan." Pohon dahan-dahan memuntir, semak botak berduri, ikan-ikan berkaki, kelinci bersisik. Memang edan. "Negeri ini tidak mati. Ada sesuatu kekuatan yang membuatnya ... begini."
"Batara Destra?"
Alitdaksa mendengus. Putra-Putri Laut memuja empat batara, dan Destra adalah batara yang Panaraban sembah. Terkenal oleh sifatnya yang perusak, pembunuh, dan pemusnah. Ayah dari segala ilmu kanuragan. "Bukan. Aku tak yakin Batara Caturkawit punya pengaruh di daerah ini. Dewa asing, kuyakin. Dewa yang tak kita kenal."
"Sahaya tak yakin suka tempat macam itu, Radén Menggung." Panaraban mengernyit. "Boleh sahaya tahu kapan kita bisa pulang ke Panjarnala?"