Aku ketakutan di balik pantat Bu Raiva.
Inginnya aku bilang di balik punggung, tetapi aku masih 7 tahun dan tinggiku hanya sampai sepinggul wanita itu. Wajahku sejajar dengan pantatnya, tanganku mencengkram rok di bawah lututnya erat-erat sampai dia tampak tak nyaman.
"Ilyas," bujuknya seraya melepas paksa genggaman tanganku dari roknya. "Ayolah. Jangan tidak sopan begitu. Itu ayahmu mulai sekarang."
Karena sudah terlalu tua untuk mengompol, aku terisak saja. Sambil gemetaran, kutelaah sosok pria super besar di hadapan kami, yang katanya ingin menjadikanku anaknya.
Pak Gun sama sekali tidak mirip figur ayah yang kubayangkan. Aku inginnya ayah yang berupa pria kurus berkacamata, rambut licin belah tengah, bungkuk, berkemeja garis-garis (sweter juga boleh), celana di atas pusar, dan sepatu pantofel. Pak Gun ukurannya dua kali manusia kebanyakan, rambutnya tidak bisa dibelah tengah karena memang tidak ada rambut sama sekali pada bulatan bercahaya yang disebutnya kepala itu. Dia memakai overalls dan kaus putih kotor di baliknya, juga sepatu bot raksasa yang sepertinya bisa melahap sekujur badanku ke dalamnya.
Aku ingin ayah yang bekerja di kantor sambil membawa tas koper; berangkat pukul 7 pagi, pulang pukul 6 sore. Pulang pukul 10 kalau lembur. Namun, Pak Gun seorang tukang pipa—dia bekerja dengan pipa. Otot-otot itu dipakainya untuk memperbaiki dan mengangkat pipa. Jari-jarinya kasar bekas menambal pipa. Bajunya dekil gara-gara pipa kotor. Dan aku benci pipa sejak insiden toilet bocor yang hampir membunuhku di dalam pipa saluran pembuangan.
"Dia memang agak pemalu," kata Bu Raiva rendah hati. Karena, ketimbang pemalu, kata yang paling tepat untuk menggambarkanku adalah penakut. "Tapi dia anak paling brilian di sini. Tidak ada anak panti sepintar Ilyas."
Tidak juga. Sebenarnya ada Toren, tetapi kurasa Bu Raiva masih ingin Toren berada lebih lama di panti, sedangkan aku ....
Sudah berulang kali Bu Raiva mencoba menyingkirkanku karena aku merepotkan, tetapi tak ada yang mau mengadopsiku. Tidak ada ... sampai Pak Gun.
"Ya." Pria itu tersenyum untuk pertama kalinya setelah beberapa menit belakangan tampak sama tegangnya denganku. "Istriku melihatnya menyelesaikan rubik ghost sebulan yang lalu."
Masih menjaga jarak, pria itu berjongkok, tangannya tertadah kepadaku. Lalu, kusadari dia menggenggam rubik ghost yang masih baru di sana, lebih bagus daripada rubik sumbangan yang sudah macet itu.
Maka pagi itu, Bu Raiva akhirnya berhasil melenyapkanku. Aku pergi dengan iming-iming sebuah rubik baru.
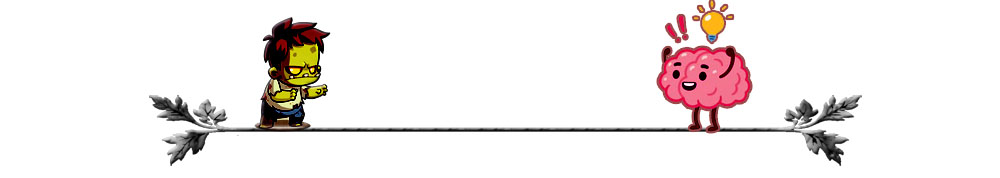
Pak Gun adalah pria pendiam yang, kalau tidak tersenyum canggung, dia akan menggosok-gosok wajahnya dengan telapak tangan untuk mengisi kekosongan di antara percakapan—entah dia bermaksud mengelap keringat atau sekadar ingin.
Setelah beberapa lama mengenalnya, aku mulai memahami kebiasaan itu. Dia seorang tukang pipa. Dia bekerja dengan lumpur, udara lembab, bau karat, berbagai jenis kotoran; dia merangkak melalui saluran-saluran pipa jalanan, sisa-sisa pembuangan perumahan, dan sampah basah penuh lemak sisa makanan di restoran dan hotel-hotel lingkungan urban. Tangan yang terangkat untuk menyeka wajah itu adalah gerakan spontan hasil dari kerja keras berjam-jam dalam sehari.
Interaksi yang terjadi di antara kami berdua hanyalah saling pandang, berdiri dalam jarak aman, saling lempar senyum canggung, lalu menggosok wajah masing-masing—aku tertular kebiasaan itu sejak hari ketiga berada di rumahnya. Makin parah sejak dia mengajakku melihatnya bekerja dan aku iseng setuju mengikutinya—berada di dekat sisa-sisa sampah organik, lumut, dan air kotor memang efektif membuat tangan tergerak melindungi wajah.
Istrinya, Bu Miriam, adalah kebalikannya—bertubuh langsing semampai, rambutnya pendek dan hitam, dia adalah wanita yang pandai memulai pembicaraan, masakannya enak, senyumnya hangat, dan senang sekali memancingku berbicara. Padahal aku benci bicara.
Rumah mereka terletak di Kompleks Lima, Jalan Triandra, Kota Renjani, hanya dua jam berkendara dari ibukota. Mereka sudah menikah selama sepuluh tahun lamanya tanpa dikaruniai anak. Mereka mengadopsiku karena Pak Gun belakangan amat sibuk dengan pekerjaannya sampai-sampai Bu Miriam kesepian sendirian.
Aku disebut sebagai jagoan kecil—kepala keluarga nomor dua setelah Pak Gun. Padahal menurutku, kepala Pak Gun saja sudah cukup untuk melindungi keluarga ini. Namun, terserah mereka saja.
Aku tidak mau sekolah. Aku takut perosotan karena pernah didorong sampai meluncur jatuh dengan posisi terbalik. Aku juga takut ayunan, dan guru-guru, dan kantin yang ramai. Aku takut ruang kelas dan meja-mejanya yang berjajar berdempetan. Aku takut teman sebangku. Jadi, Bu Miriam menyekolahkanku di rumah. Dia sendiri yang mengajariku lewat buku-buku.