Aku anak pertama yang melihat lubang di tembok itu, tetapi Ifan yang pertama mengumumkan, "Masuk ke sini, yok!"
Yang lain menyahut, "Ayok!"
Sekumpulan anak berumur 8 tahun tidak tahu apa-apa, tetapi aku tahu. Di sisi lain tembok ini adalah Neraka. Ibuku sering menceritakan kengerian yang terjadi berdekade lalu saat Nusa masih belum dilindungi tembok: makhluk pemakan otak, gigi-giginya setajam taring harimau, kukunya seruncing cakar beruang, dan gigitannya beracun. Kuceritakan apa yang ibuku ceritakan, lalu aku ditertawakan.
"Zombie itu nggak ada!" Ifan menukas. "Kakakku bilang, itu cuma akal-akalan orang dewasa supaya kita nggak main jauh-jauh atau pulang kemalaman."
"Kakakmu, 'kan, di penjara gara-gara berbuat jahat." Aku mengingatkannya.
"Kakakku cuma dimarahi Bapak Polisi itu, nggak dibawa ke penjara!" Wajah cowok itu memerah marah. "Dan lagi kakakku nggak jahat! Dia cuma main petasan, petasannya nyasar ke rumah orang—itu aja!"
"Petasannya yang salah." Dwira mengangguk-angguk menyetujui. "Kalau kamu nggak suka main sama kami, Cal, main sendiri saja! Sana!"
Segerombolan anak itu, yang Ibu bilang adalah teman-temanku walau aku tidak merasa demikian, mulai berebut untuk menjejalkan diri ke dalam lubang di tembok W. Mereka saling dorong dan tarik, tetapi lubang itu masih terlalu kecil untuk dilalui, bahkan oleh Vivi yang badannya paling kecil di antara kami.
"Cal! Gedein lubangnya dong!" tuntut Vivi.
Aku mengerjap. "Caranya?"
"Pukul, tendang, atau apalah! Kamu, 'kan, kuat!"
Dipuji begitu, aku jadi melupakan cerita Ibu tentang zombie atau fakta bahwa anak-anak itu sempat menyuruhku main sendiri. Aku mendekati lubang, mengeruk dan menggali semennya yang keropos dengan tangan, menggedornya pakai lutut dan mengoreknya dengan ujung sepatu.
Lubangnya membesar sedikit, cukup untuk kepala Vivi, tetapi kemudian aku melihat kelebatan bayangan di baliknya.
Ada sesuatu yang bergerak di balik tembok.
"Anak-anak nakal!" Serge—seorang pria tua yang rumahnya berdempetan dengan tembok W—berteriak dari jendela lantai atas rumahnya.
Pria itu veteran perang. Perang apa, aku tak tahu. Sebelah matanya picak, satu kakinya pengkor, dan satu tangannya kutung sampai pergelangan. Walau demikian, pria itu bisa lari pincang dengan cepat, lemparannya jitu, dan dia bisa mengenali wajah anak-anak bandel dari jarak jauh. Dia adalah mimpi buruk di wilayah kami.
Barang-barang melayang keluar dari jendela Serge: mangkuk plastik berisi air ludahnya, tongkat kayu, dan sendok sayur beterbangan ke arah kami. Bidikannya hebat sekali. Mangkuk peludahannya mendarat jadi topi di atas kepala Ifan.
Kami menjerit dan berlarian. Ifan menangis paling keras, terbirit-birit berkeliling bundaran air pancur yang sudah kering. Mangkuk masih di atas kepalanya.
Kami mengadu ke orang dewasa, tetapi mereka bilang Serge tidak bisa diapa-apakan.
"Toh, sebentar lagi kakek itu bakal mati, biarkan saja," kata seorang pria di warung kopi saat kami heboh bercerita. "Lagi pula, kalian juga salah. Kenapa main berdekatan tembok begitu? Di sana banyak sampah, barang berbahaya, dan monster! Kalian tidak takut zombie? Mereka berkeliaran tepat di sisi seberang sana, di balik tembok! Tembok W ini perbatasan antara Nusa dan Neraka!"
Saking seringnya ditakut-takuti tentang zombie, ancaman itu jadi terasa tumpul. Aku bahkan sudah lupa tentang bayangan di balik tembok itu.
Aku juga lupa perihal lubangnya.
Kami tidak pernah main lagi di dekat sana karena takut dilempari barang-barang oleh Serge. Lokasinya yang dekat peternakan juga sudah cukup mengusir siapa pun yang tidak punya kepentingan—anjing gembalanya menggonggong terus-terusan.
Tersembunyi di balik tumpukan papan kayu bekas dan pipa-pipa raksasa bekas galian serta segunung sampah, tempat itu makin terisolasi. Serge yang pemarah dan bau busuk bangkai sapi ternak yang terlambat dibersihkan pun perlahan membuat pemukim setempat menjauh—mereka lebih memilih merantau ke kota atau tinggal bersama keluarga mereka di distrik sebelah.
Sampai tiga tahun kemudian, saat umurku 11 tahun, sekumpulan wanita pengrajin barang bekas memutuskan untuk memulung di sana. Mereka menemukan lubang di tembok yang kini muat untuk dilalui oleh satu orang dewasa. Di tepi-tepi lubang pada semen keropos, terdapat jejak darah kering dan cuilan daging tersangkut. Jejak itu seperti diseret sampai menghilang ke tumpukan sampah.
Nusa menetapkan kondisi darurat nasional untuk pertama kalinya sejak hampir 70 tahun lamanya.
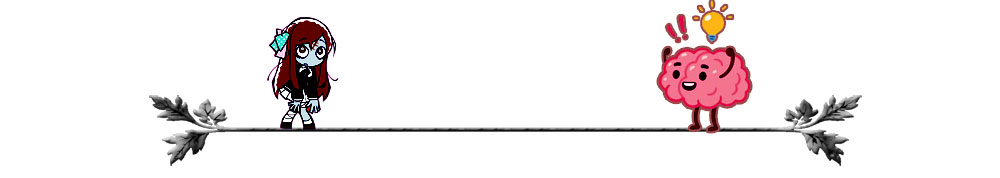
"Aku tidak mau pindah," lirihku seraya mengangkat setas penuh pakaian kami.
"Tempat ini sudah tidak aman, Sayang," bujuk Ibu saat mengambil alih tas dari tanganku. "Beberapa hari lagi akses jalan masuk kota akan ditutup, jadi harus sekarang. Orang-orang di tempat ini akan pindah semua. Teman-temanmu juga."
"Tapi mereka pindah ke rumah kerabat," gerutuku. "Kita malah dijejalkan ke rumah susun dengan tiga keluarga lain."
"Kita tidak punya kerabat lagi, Cal."
"Bagaimana dengan Om dan Tante? Kakek dan Nenek?"
"Mereka tidak pernah menghubungi lagi sejak ...." Ibu berhenti sebentar. "Sejak ayahmu meninggal."
Jeda lagi untuk sesaat. Mata Ibu memerah dan suaranya bergetar sedikit. "Maaf, Sayang, andai saja ada keluarga dari pihak Ibu yang tersisa ...."
Aku masih tidak suka kalau harus tinggal di rumah susun, tetapi aku juga tidak mau membuat Ibu sedih, jadi aku menggandeng tangannya dan menutup mulutku.
Kami naik ke atas bak mobil pikap yang menyediakan tumpangan massal ke kota. Si Tua Serge mengeluarkan kepala dari jendela rumahnya dan meludah sembarangan, lalu menatap kami semua dengan senyum mencela. "Wah, lihat ini. Sekumpulan wanita yang akan menjanda dan anak-anak calon yatim-piatu, berbondong-bondong ke kota untuk disantap otaknya oleh zombie."
Aku menggertakkan rahang. Padahal pria di warung kopi berjanji Serge akan mati tak lama lagi. Sudah tiga tahun berlalu, pria tua ini masih di sini. Kalau pun dia pernah mendapat firasat diintip malaikat maut, Serge tak menunjukkannya.
"Anda tak ikut kami ke kota, Pak?" tanya ibuku sopan. Kalau itu aku, aku takkan punya waktu untuk sopan santun. Aku pasti sudah mengambil alih setir mobil pikap ini dan menabrakkan diri ke pintu depan rumah Serge. Si pria tua beruntung kakiku belum sampai ke pedal gas.
"Dan berkumpul dengan lautan manusia yang akan menarik para zombie ke tengah kota? Tidak, terima kasih." Serge meludah lagi. "Daripada mati dimakan zombie atau terinfeksi, lebih baik aku membusuk di sini. Sendirian."
"Semoga permohonan kecilmu itu dikabulkan Yang Mahatinggi—" Ibu menyentakkan tanganku sampai aku tutup mulut.
Mesin mobil dinyalakan. Diiringi gerutuan dan suara batuk berdahak Serge, mobil pikap berjalan dengan lambat. Kusempatkan diri untuk menoleh, mengamati lingkungan itu untuk terakhir kali.
Distrik Nava memang kumuh dan seringkali mendapat sorotan nasional karena lokasinya yang terlalu dekat dengan Tembok W, tetapi aku lahir dan dibesarkan di sini. Ada kenangan ayahku di sini. Saat ibuku dan aku bepergian ke kota untuk menemui kerabat atau bekerja, kami selalu pulang kemari. Memikirkan bahwa kami mungkin takkan kembali lagi ke sini ... rasanya seperti ada yang mencabut sebelah kakiku dan meninggalkannya di sini, lalu memaksaku pergi.
"Jangan menoleh, Nak," kata seorang pria berjanggut yang duduk di seberangku. Kepalanya tertutup terpal bolong-bolong untuk berlindung dari teriknya matahari. "Kau tahu apa kata orang zaman dulu—kemungkinan besar kau akan kembali lagi ke tempat itu jika menoleh ke belakang."
Dalam rumah susun, kami dijejalkan bersama lima orang asing: dua remaja dengan masing-masing ibu mereka dan seorang wanita pemabuk yang masih lajang.
Dua cewek remaja lainnya yatim sepertiku, dan ibu mereka bekerja serabutan persis ibuku, tetapi cuma itu kesamaanku dengan mereka. Keduanya sebaya dan sama-sama berasal dari Distrik Nefrit—hanya 7 kilometer dari distrik tempatku berasal. Mereka sudah membentuk tali persahabatan super erat dan selalu berdua ke mana-mana untuk menghindari kewajiban mengajakku bicara.
Meski masih ada anjuran untuk tak keluar rumah, peraturan mulai melonggar. Sudah tiga minggu sejak lubang itu ditemukan, tiap wilayah disisir dari sudut ke sudut, tetapi tak ditemukan satu zombie pun. Lagi pula, korban para zombie selalu mudah dikenali—batok kepala menganga, tengkorak rusak, otak yang hilang, dan bekas gigitan di sekujur tubuh. Atau korban tergigit—yang bertransformasi menjadi zombie sebelum otaknya dimakan—yang malah lebih mudah lagi dikenali. Namun, semuanya masih tampak normal. Tidak ada gerombolan zombie yang berbaris mencari otak di jalanan.
"Lubang di tembok, 'kan, sudah ditutup," gerutu Ulli siang itu saat kami berkumpul bertiga di kamar. "Para polisi pasti juga sudah menemukan zombie yang sempat masuk. Ibuku sudah bekerja. Tapi kenapa kita masih tidak boleh keluar?"
Nayna berdecak. "Polisi Nusa pasti masih mencari agar lebih yakin saja bahwa tidak ada zombie lain."
