Nusa adalah satu-satunya peradaban manusia yang tersisa selama 70 tahun lamanya sejak Desember 2099, dan teritori di luar Tembok W telah menjadi Neraka—atau sebatas itulah yang kami ketahui selama ini.
Nusa pernah memiliki pasukan militer khusus untuk mencari peradaban lain dan mencoba mengontak negara yang barangkali masih tersisa—dari 13 regu yang dikirim, hanya dua regu yang kembali dengan masing-masing separuh anggotanya menghilang. Sepuluh di antaranya terinfeksi dan segera dieksekusi. Hanya tiga tahun sejak terbentuknya, pasukan itu dibubarkan.
"Meski ada peradaban yang selamat di luar sana, besar kemungkinan mereka bukannya akan memberi bantuan dalam krisis zombie, melainkan memberi beban tambahan." Mantan Kepala Militer Nusa memberi pendapat 60 tahun silam dalam film dokumenter Krisis Nusa 99. Film itu terus diputar ulang tiap tahun di televisi pada bulan Desember. "Nusa harus memprioritaskan kemaslahatan rakyatnya di atas segala-galanya. Pegang kata-kata saya, bahkan untuk seratus tahun—tidak, tidak! Menurut saya, bahkan untuk satu milenium ke depan, Nusa masih dan akan terus bertahan di dalam lingkar Tembok W. Maka dari itu, misi pencarian bantuan ke dunia luar baru akan dilanjutkan kembali setelah kita menata ulang negeri—"
Aku mematikan televisi. Setelah penemuan lubang di tembok W dan menghilangnya Pak Gun 8 bulan silam, si Kepala Militer itu terkesan seperti penipu di mataku.
Setelah lubang pada tembok ditambal, keadaan berangsur kembali tenang. Zombie yang menyeberang tak kunjung ditemukan. Tidak ada siaran beritanya. Menurut orang-orang, itu hal bagus. Menurutku tidak. Kalau memang tidak ada zombie, kenapa tidak disiarkan saja perkembangannya? Tidak ada berita bukan berarti tidak ada bahaya sama sekali.
Sekarang, semua orang tampaknya sudah lupa perihal lubang pada tembok. Bahasan zombie hanya sekadar lewat dan sebagian besar siaran didominasi hari jadi Nusa yang ke-70. Emma baru genap 7 bulan saat parade ulang tahun Nusa diadakan. Arak-arakan berlangsung seminggu penuh dan sudah dua kali lewat di jalan depan rumah kami, balon-balon dilepas ke langit, dan musik mengusik udara. Emma makin rewel karena kesulitan tidur. Dia terus menangis siang dan malam, terserang demam atau masuk angin hampir tiap saat.
Dokter sudah pernah memperingatkan kalau pertumbuhan Emma mungkin akan terhambat dari anak lain dan imun tubuhnya lemah karena lahir prematur, tetapi Bu Miriam meyakinkanku kalau kami bisa melewati keadaan ini bersama, meski tanpa Pak Gun sekali pun.
"Jangan pikirkan masalah uang, oke?" Bu Miriam berkata saat aku terkejut melihat daftar pengeluaran kami bulan itu. Sejak Pak Gun tidak ada, Bu Miriam harus kembali mengajar kursus anak-anak sekolah. Maka, dia butuh pompa ASI dan tempat penyimpanannya untuk Emma.
Bu Miriam pernah mencoba menyewa pengurus dan pengasuh beberapa kali, tetapi selalu terjadi masalah—pengurus rumah tangga yang sudah tua dan teledor membiarkan Emma di ayunan bayinya tanpa susu sampai sore, pengasuh muda yang kelayapan meninggalkanku dan Emma berdua di tengah jam kerja, sampai seorang tukang cuci yang membujukku mengerjakan tugas-tugasnya tanpa diketahui Bu Miriam (dia diberhentikan setelah ketahuan).
"Sejak aturan isolasi di rumah melonggar, makin banyak yang memanggil guru privat untuk mengejar ketertinggalan." Bu Miriam menunjuk jendela, mengisyaratkan arak-arakan pawai yang masih berlangsung. "Kau boleh main keluar kalau kau mau, Ilyas. Belilah sesuatu."
"Aku di sini saja," kataku seraya mengamatinya mengganti popok Emma. "Apa kami harus dititipkan pada Nenek Aya lagi?"
Nenek Aya sudah agak pikun dan kacamatanya setebal pantat botol. Hobinya mengoceh tiap saat, bahkan saat tak ada orang di dekatnya. Aku tak pernah tahu apa yang dibicarakannya. Namun, Nenek Aya adalah satu-satunya tetangga menganggur yang kami punya. Satu-satunya tempatku dan Emma mengungsi kalau Bu Miriam harus pergi ke luar.
Bu Miriam mendesah, "Aku khawatir, kalian harus berdua dulu sehari ini. Nenek Aya sedang sakit—kenapa kau menyengir begitu?"
"Tidak apa-apa." Aku buru-buru mengatur wajah. "Aku bisa mengurus Emma."
Bu Miriam meragu sesaat. "Aku hanya mengajar sampai pukul 2 siang hari ini. Makanan sudah ada di atas meja. Susu untuk Emma di tempat biasa."
Aku memberitahunya bahwa aku sudah ingat dan paham semuanya, lalu berjanji dia takkan perlu mencemaskan apa pun.
Setelah Bu Miriam pergi, aku merapatkan semua pintu dan jendela untuk meredam suara bising di luar. Kututup tirai rapat-rapat karena jalanan ramai oleh pejalan kaki—stan jajanan memenuhi tiap sisi trotoar, kertas warna-warni mengotori jalan, dan sesekali ada saja orang yang berkaca untuk membenarkan rambut di kaca jendela rumah kami.
Seharian, aku menonton televisi dengan volume kecil di samping Emma. Berita dipenuhi peringatan ulang tahun Nusa: upacara di ibu kota, pawai di beberapa distrik, pertunjukan dan berbagai kompetisi berhadiah besar, sampai pemutaran film-film lawas tentang sejarah dan drama perjuangan pasukan elit Nusa 70 tahun lalu yang memberantas para zombie.
Adikku merengek dalam tidurnya dan perlu ditepuk-tepuk agar kembali pulas. Mataku melirik kaca jendela sesekali, di mana orang-orang tertawa dan mengobrol. Karena sekolah masih libur, sesekali terdengar suara anak-anak seusiaku, berlarian dan meneriaki orang-orang berkostum yang tengah pawai. Harum sosis dan jagung bakar tercampur, masuk lewat ventilasi.
Sebentar lagi pukul 2. Aku bisa minta dibelikan Bu Miriam ....
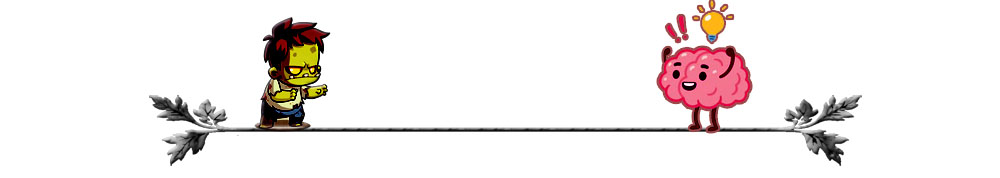
Sampai pukul 3, Bu Miriam tak kunjung pulang.
Aku mondar-mandir di dekat jendela, mengintip keluar untuk mencari Bu Miriam, lalu mundur lagi saat ada orang asing yang terlalu dekat dengan rumah.
Pukul 4, Emma mulai merengek panjang. Pawai makin ramai, aroma jajanan makin kuat. Namun, aku tidak bisa keluar karena; pertama, aku tidak pernah membeli barang sendiri; dan kedua, Emma tidak bisa ditinggal.
Pukul 5, terdengar suara debuman keras.
Aku mengintip di balik tirai dengan dada berdebar. Tak jauh dari rumah, sebuah mobil pikap terbalik di sisi jalan. Aku buru-buru naik ke lantai atas untuk melihat lebih jelas. Beberapa pejalan kaki melintas di depan rumahku ke arah mobil pikap, tampaknya hendak melihat apa yang terjadi, tetapi mereka terus bertabrakan dengan arus orang-orang yang mencoba melawan arah.
Baru kemudian kusadari, arus yang melawan arah itu mati-matian menjauhi mobil pikap. Beberapa di antaranya mulai meneriaki orang-orang untuk pergi atau minggir dari jalan mereka.
Mobil pikap yang terbalik itu salah satu peserta pawai. Ada sekitar tiga orang berkostum tentara dan dua orang beriasan wajah zombie yang diangkutnya, tampak berjuang untuk menjauhi mobil pikap. Beberapa hiasan mobil rusak dan berceceran, seutas pita panjang membelit si sopir yang berusaha keluar. Iring-iringan jadi macet di belakangnya.
Beberapa orang masih berusaha menonton mobil yang terbalik, tampak kebingungan di antara kerumunan, sedangkan yang lainnya sudah berdesak-desakkan menjauhi mobil sambil meneriaki kerumunan lainnya idiot. Kulihat ada yang mulai menggedor-gedor pintu rumah di sekitarnya, mencoba memaksa masuk.
Dua orang pria dan satu wanita asing kemudian mendekati rumah kami. Mereka mengetuk pintu dan meneriakkan sesuatu yang tak kudengar dengan jelas. Saat mereka mendongak dan melihatku di balkon, mereka berteriak lebih kencang kepadaku. Aku mundur dengan gugup, lalu menutup pintu balkon karena takut.
Aku turun ke ruang tengah untuk mengangkat Emma. Sambil mengabaikan orang-orang aneh yang masih memaksaku membuka pintu, aku membawa adikku ke kamar Bu Miriam dan mengunci pintu. Setelah orang-orang yang memaksa masuk itu pergi, datang lagi orang lain yang mengetuk pintu depan. Makin lama jumlahnya bertambah, dan suara mereka makin keras.
Emma mulai menangis di atas tempat tidur Bu Miriam, jadi aku menggendongnya sampai dia tenang. Namun, tiap aku meletakkannya kembali, Emma menangis lebih keras, lebih histeris.
"Emma, tanganku sakit," kataku. "Tidurlah, ya ... kumohon."
Dia tidak setuju. Tangannya berpegangan bahuku. Saat tubuhnya kurendahkan ke atas tempat tidur Bu Miriam, Emma menjerit. Aku mencoba duduk sambil masih menggendongnya, tetapi Emma juga tidak menyukainya. Tangisannya mereda hanya jika aku berjalan mengelilingi kamar sambil menggendongnya.
"Emma ...." Aku mengerang. "Tangan dan kakiku sakit ...."