Tak lebih dua minggu yang lalu Bu Miriam pergi, kami menguburkannya di halaman belakang rumah di malam tahun baru, tetapi aku tidak bisa berkabung lama-lama. Tiap kali aku tidur lebih lama di atas ranjang, berselimut sambil terisak-isak, Emma akan menangis lebih keras.
Sudah empat tetangga yang menawarkan diri untuk memanggil petugas sosial atau memasukkan kami ke panti asuhan sejak Bu Miriam tiada. Aku selalu menolak—aku tahu rasanya masuk panti. Aku akan bertemu dengan Bu Raiva lainnya di panti mana pun, dan aku takut aku tidak akan diadopsi sepaket dengan Emma—kami bukan saudara kandung.
Lagi pula, kami masih punya Nenek Aya. Si nenek kini tinggal sendirian. Anaknya yang masih bujangan tidak ada kabarnya lagi sejak serangan zombie hari itu. Kini beliau hidup sendiri, bertahan sehari-hari dengan jatah dari pensiunan mendiang suaminya yang selalu dikirim oleh pos tiap bulan.
Ada semacam hubungan mutualisme di antara kami—aku mengurus si nenek di hari tuanya dan (terutama) mengatur kadar gula di makanan/minumannya; sedangkan Nenek Aya membiayai kebutuhan sehari-hariku dan Emma. Aku mulai terbiasa dengan ocehan melanturnya, dan para tetangga memaklumi hubungan ini.
Sejak serangan zombie terjadi, krisis nasional berlangsung. Karantina di rumah dan jam malam diperpanjang sampai batas waktu tak menentu, tenda-tenda militer didirikan di semua ruas jalan, angkutan umum dilarang beroperasi, dan hampir semua kegiatan jual-beli harus dilakukan melalui organisasi kurir yang disetujui pemerintah.
Rumah demi rumah mulai membangun pelindungnya masing-masing—pagar tinggi, jebakan-jebakan di halaman, palang pintu. Sudah tidak sedikit orang-orang yang menyimpan senjata api dalam rumah. Saluran televisi dan radio pun mulai berkurang, tetapi berita penyerbuan zombie masih tersebar. Beberapa perkampungan telah lumpuh total.
"Tempat teraman adalah perbatasan," kata Nenek Aya saat aku mengunjunginya suatu siang. Di kursi goyangnya, dia memangku Emma. Sementara aku membuatkan teh untuknya. "Dalam keadaan seperti ini, zombie-zombie itu akan mendatangi tempat yang ramai oleh manusia—iya, 'kan, Nak?"
Aku menaruh cangkir teh di atas meja di samping kursinya. "Nenek, Anda ingin aku memesankan sup seperti kemarin atau bubur saja?"
"Ya, nasi sudah menjadi bubur. Yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan. Kita bisa mengurung diri dalam rumah, atau lari ke perbatasan seperti kataku tadi."
"Bubur, kalau begitu." Aku menelepon. Sejak sebulan yang lalu, bisnis jasa kurir jadi berkembang pesat. Orang-orang takut keluar rumah, maka mereka memesan segalanya lewat telepon.
Para kurir kini jadi semacam kelompok eksklusif karena mereka mendaftar untuk pekerjaan yang secara harfiah menggantungkan nyawa mereka. Mereka diberi izin untuk membawa senjata, mendapat subsidi besar untuk kendaraan dan seragam khusus, kadang mendapat pengawalan langsung dari personel militer saat bertugas, dan tak jarang pula personel militer sendiri yang merangkap jadi kurir.
Sebut aku gila—aku sempat mempertimbangkan untuk mendaftar jadi kurir sehari setelah kematian Bu Miriam. Pak Gun dan Bu Miriam tidak meninggalkan pensiunan, hanya sekumpulan kenalan yang sesekali mengirimi kami uang sebagai belas kasih. Emma masih butuh susu formula khusus, baju, dan ... yah, segala hal.
Aku merenung di kamar mandi hampir dua jam, mempertimbangkan seberapa tinggi kemungkinan aku bisa bertahan hidup kalau aku jadi kurir. Aku pada dasarnya buta arah karena jarang keluar rumah. Aku tidak bisa naik kendaraan apa pun. Kemungkinan besar, aku akan kesasar ke sebuah gang di hari pertama dalam perjalanan menuju warung dan dicamil zombie hidup-hidup. Aku bakal meninggalkan Emma sendirian di bawah asuhan Nenek Aya yang rabun dan pikun.
Yah, pada akhirnya, Nenek Aya punya alternatif lain. Gaji pensiunan mendiang suaminya lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari kami bertiga, dan—seperti yang sudah kusinggung sebelum ini—Pak Gun dan Bu Miriam punya banyak kenalan yang hebat dan murah hati.
Seperti kemarin, misal, saat Kepala Polisi sendiri—Randall Duma—menelepon ke rumah kami dan mengirimiku berbagai macam jebakan zombie yang mereka kembangkan di ibukota. Dia mengirimkan beberapa pesuruhnya untuk memasangnya langsung di halaman belakang serta pintu depan.
"Nenekku dulu pernah bercerita tentang sesuatu yang ajaib," kata Nenek Aya lagi. "Mirip telepon, tapi bukan telepon. Mereka menyebutnya internet. Satu kali klik, dan segalanya bisa kau dapatkan. Kurir langsung datang. Kita bahkan bisa menghubungi orang-orang yang jauh sekali."
"Nenek, aku mau mengganti popok Emma." Kuambil alih adikku dari pangkuannya. "Nenek tidurlah. Nanti kalau buburnya datang, akan kubangunkan."
"Ya, ya, nenekku juga ikut membangunnya. Dia bilang, dia menyesal. Sistem itu melumpuhkan semua yang telah dibangun umat manusia. Tidak ada lagi internet. Pesawat-pesawat pun dibatasi. Mereka bahkan merevisi sejarah. Masalah zombie membuat mereka kehilangan akal."
Nenek Aya masih mengoceh, tetapi aku berhenti mendengar. Selama setengah jam berikutnya, aku bergulat dengan Emma yang menolak berganti popok dan bersikeras menyarangkan kakinya di wajahku.
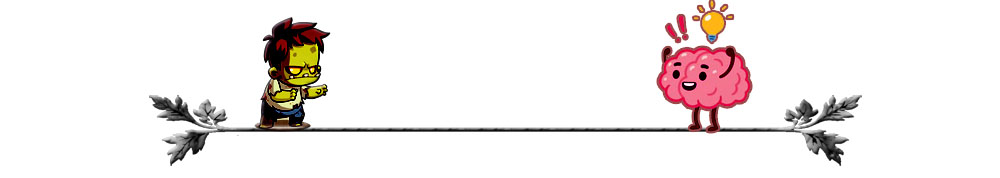
Kurir tidak selalu ramah. Karena hampir kebal hukum, disokong orang militer, dan punya izin menggunakan senjata, beberapa dari mereka memanfaatkannya dengan maksimal. Ada yang meminta bayaran tak masuk akal, ada yang menjarah rumah-rumah yang mereka datangi, ada yang memaksa masuk dan berbuat jahat—terlebih jika penghuni rumah hanya perempuan dan anak-anak.
Mereka biasanya pakai kartu 'aku membahayakan hidupku di luar sini, jadi biarkan aku masuk'. Meski ada sistem ulasan dan aduan pelanggan, 30% kurir tetap lolos dari jerat hukum dengan memeras klien yang jadi korbannya.
Cara paling aman bagiku menangani itu adalah meninggalkan uang di bawah keset kaki, lalu menunggu di depan pintu yang terkunci. Aku hanya perlu memberi tahu si kurir dari balik pintu untuk meletakkan pesanan di luar dan mengambil uang di bawah keset, lalu kuambil barangnya setelah mereka pergi.
Cara itu berhasil jika kurirnya lumayan ramah. Kadang, beberapa kurir ngotot beralasan kalau uangnya kurang atau mengancam bakal merusak barang pesanan. Maka, aku harus menembakkan pistol dengan peluru kosong sampai dia pergi. Pistol ini kudapat dari Randall Duma sendiri. Tidak berbahaya, tetapi ia membuat bunyi keras yang akan menciutkan nyali si kurir.
Aku memantau keadaan lewat jendela selama dua menit, membuka pintu rumah si nenek dengan jantung berdebar, lalu cepat-cepat menaruh uang di bawah keset kaki. Kututup pintu kembali dengan tubuh yang sudah basah kuyup oleh keringat dingin.
Aku selalu gemetar jika menunggu kurir di depan pintu. Sambil berharap aku tidak perlu memakai ancaman pistol dengan peluru kosong, aku memelototi pintu dan terus dihantui bayang-bayang Bu Miriam yang mati di depan pintunya sendiri.
"Diam dulu, Em," kataku saat Emma bergerak-gerak di pangkuanku. Adikku menggeliat, merosot, mengerut sampai kunaikkan lagi dan dagunya bersandar di bahuku. "Kalau tidak mau diam, kau bakal kukembalikan ke pangkuan si nenek."
Adikku pintar. Dia mengerti dan langsung diam.
"Aku ingat saat harga mi instan masih terjangkau uang jajan anak sekolahan," kata suara di belakangku, membuatku berkedut kaget. "Harganya sempat melejit di zaman ibuku karena krisis."
"Nenek duduk saja di dalam," kataku buru-buru. Kusimpan pistol ke bawah kakiku. "Di sini berbahaya dan dingin Masuklah, Nek. Tidur, atau nonton tv."
"Kenapa kau tidak sekolah, Nak?"
Aku melipat bibir ke dalam. "Aku tidak begitu suka ditempatkan di antara banyak orang. Lagi pula, Bu Miriam mengajariku."
"Ah, Miriam yang baik hati." Nenek Aya mengangguk-angguk, lalu duduk membungkuk di sisiku. Kaki-kakinya yang kurus menyilang. "Dia senang sekali saat bercerita bahwa dia dan suaminya akan mengadopsi seorang anak."
Aku mengedip untuk melenyapkan air mata. "Itu aku, Nek."
"Namanya kalau tidak salah Ilyas," lanjutnya begitu saja. "Menurutmu, di mana anak itu sekarang?"
"Aku Ilyas."
Nenek Aya mengerjap-ngerjap. Dari balik kacamata tebalnya, matanya memicing, mengamat-amatiku. Dia melepas kacamatanya sebentar, mengelapnya dengan dada bajunya, dan memasangnya kembali. Si nenek lalu terbahak sampai terjadi hujan lokal ke wajahku. "Oh, kau Ilyas, toh! Kukira kau Emma!"
"Ini Emma!" Kusodorkan Emma ke depannya sampai adikku merengek protes. "Emma adik perempuanku, umurnya belum setahun! Aku Ilyas, yang diadopsi!"
"Oh, betul!" Si nenek masih tergelak. "Ya, ampun—kau cepat sekali besar!"
Pikun si nenek tampaknya sudah akut. Padahal sudah bertahun-tahun lewat sejak aku diadopsi, dan dua bulan lagi aku sudah dua belas. Apakah dia pikir aku masih 8 tahun?
Begitu aku menarik Emma kembali, pintu diketuk. Kurir kami sudah tiba.
"Uangnya di bawah keset," kataku. Sudah berkali-kali aku mengatakannya, tetapi suaraku tetap bergetar. "Tolong tinggalkan saja paketnya di depan pintu. Terima kasih."
Aku menyibak tirai jendela dan mengintip. Si kurir masih di sana.
"Boleh aku minta kopi?" tanya si kurir. Keningnya dia tempelkan ke kaca jendela. Tidak ada orang militer yang mengawalnya sejauh yang kulihat. Dia sendirian. "Aku belum tidur sejak semalam. Tolong."
Aku menelan ludah. Kuserahkan Emma ke tangan si nenek dan menyuruhnya masuk ke dalam. Kuambil pistol ancamanku. "Pergilah. Kami tidak punya kopi!"
"Air putih saja kalau begitu," desaknya. Aku baru akan melepaskan tembakan, tetapi si kurir melanjutkan, "Aku akan beri tahu kau sesuatu yang berguna sebagai gantinya. Dan ... pokoknya buka saja. Cepat."
Lalu, aku melihat alasannya memaksa masuk. Dari seberang jalan, kulihat sosok ceking bersinglet penuh bercak darah, melangkah lambat keluar dari gang. Matanya yang putih fokus pada punggung si kurir, mulutnya membuka-tutup.