Serge menganggapku lucu. Dia bahkan tertawa saat aku menceritakan penembakan di bus itu dan kematian ibuku.
Semalaman aku mengejarnya berkeliling meja makan di dapurnya yang kotor, mencoba mencekik si kakek tua. Sialan, Serge benar-benar tidak seperti manula kebanyakan. Dia menghindariku dengan mudah sampai aku kelelahan sendiri. Bahkan saat aku melemparkan pentungan Pak Radi, Serge mampu membungkuk tanpa mematahkan tulang belakangnya sama sekali.
Karena tidak mampu menyakitinya secara fisik, kuhabiskan seluruh makanan di dapurnya, lalu menenggak tiga gelas teh sampai perutku sakit. Sementara dia mencak-mencak dari jendelanya, aku menyeret sepeda menuju rumah lamaku.
Rumahku, kalau debu tebal dan bau apaknya tidak dihitung, sama sekali tidak berubah. Aku bersyukur kami meninggalkan pakaian ayah di kamarnya karena nilai sentimental semata. Beberapa bajunya sudah dimakan rayap, atau menempel karena basah bekas rembesan air bocor dan langsung hancur saat aku memisahkannya. Namun, dua helai kemeja dan celana belelnya masih utuh di tengah-tengah.
Aku menimba air sumur kami yang tak pernah kering, lalu mandi sampai tak lagi tersisa bekas darah siapa pun di badanku. Kupakai baju tua ayah begitu saja, lalu bergelung di atas kasur lamaku. Aku menangis sampai tertidur.
Besok paginya, badanku gatal-gatal.
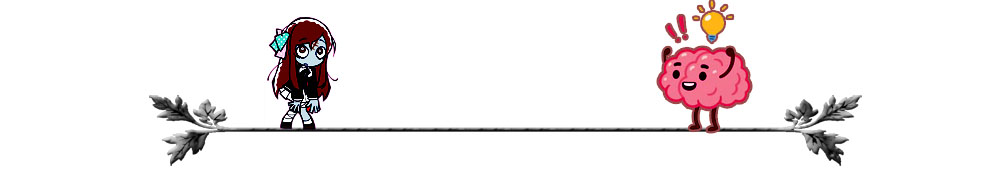
Menjadi babu Serge bukanlah pilihan, tetapi keharusan.
Si pria tua mengajariku macam-macam, termasuk kesabaran—dibutuhkan ketabahan seluas tanah Nusa untuk menghadapinya. Aku menimba air di sumur buatnya, menebang kayu, memberi makan dan mengembangbiakkan ternak-ternak, dan menyembelih hewan sendiri—lalu diwajibkan mendengarkan keluhan-keluhannya tentang rasa air yang tengik dan alotnya olahan daging kambing yang kami makan.
Selama perbatasan ditinggalkan, Serge melakukan itu semua sendiri. Setelah ada aku, dia menggunakan kartu 'aku sudah tua' dan 'tanganku cuma satu' untuk memperbudakku di bawah kakinya; sedangkan aku tidak diizinkan sama sekali pakai kartu 'aku masih 11 tahun' terhadapnya.
Setidaknya, dia mencuci pakaiannya sendiri. Aku tidak sudi menyentuh kain-kain usang berjamur dan bau masam yang dia sebut baju itu.
Pagi-pagi buta, kami sarapan di rumahnya sebelum mengerjakan tugas masing-masing, makan siang sendiri-sendiri, lalu makan malam bersama lagi. Karena tidak mau mendengarkan ocehan satu sama lain, kami mendengarkan radio. Tidak banyak yang bisa didengar kecuali lagu-lagu lawas yang berulang tiap hari.
Dua minggu setelah kejadian biadab di bus itu, aku sudah hampir tidak pernah mimpi buruk lagi, tetapi mustahil bagiku melupakan tiap detailnya. Aku masih ingat wajah orang-orang berseragam militer itu, terutama tiga wajah: kapten mereka yang melapor 'tugas selesai' dengan santai melalui alat komunikasinya, dan dua prajurit yang membiarkanku kabur.
Mereka pasti mengangkat senjata juga meski tak menginginkannya—dari raut wajah dan percakapan keduanya, mereka hanya mengikuti perintah dan sebagainya. Dua prajurit itu bisa saja langsung membunuhku, atau menangkapku dan memberikanku ke kapten mereka. Namun, mereka justru menyuruhku lari. Walau sebetulnya, akan lebih baik kalau mereka membantuku—mungkin ibuku masih bisa dilarikan ke rumah sakit?
Atau, akan lebih baik lagi kalau mereka tidak menembaki siapa-siapa dari awal ....
Atau, jauh akan lebih baik lagi kalau Cal kecil yang tolol tidak tolol tiga tahun lalu. Kalau aku melaporkan lubang itu lebih cepat, mungkin ini takkan pernah terjadi.
Pagi-pagi buta sekitar pukul 2 pagi, karena aku tidak mau Serge melihatku, kugali tanah di depan rumahku. Kusiapkan dua liang lahat yang dangkal. Kulemparkan sebagian besar baju ibuku ke salah satu lubang, lalu secarik kecil sarung Pak Radi ke lubang satunya. Kumakamkan keduanya dan menandainya dengan kayu serta setangkai kamboja.
"Ibu," kataku pada kuburan bajunya. Kutangkupkan wajahku ke kedua lengan yang terlipat memeluk lutut. Sarung Pak Radi yang sudah agak robek terlipat di sampingku. "Apa nyawamu dan semua orang di bus itu hilang gara-gara aku? Apa aku bakal di penjara? Kalau tiga tahun lalu aku tidak memperbesar lubangnya, atau langsung melaporkannya, pasti tidak akan begini, 'kan? Kita masih ada di sini. Kau masih memeluk dan memarahiku tiap hari. Pak Radi masih terenyum di pos jaganya di rumah susun sana."
Aku berkabung selama beberapa menit, lalu berjalan gontai ke rumah sambil menyampirkan sarung Pak Radi ke bahu. Sebelum melewati pintu, kusadari lampu kamar Serge masih menyala dan jendelanya masih terbuka. Apa dia melihatku menangis barusan?
Karena penasaran, aku menyambangi rumahnya. Dia tidak pernah terjaga sampai selarut ini.
Di depan pintunya, aku mendengar suara gelombang statis dan banyak sekali noise radio. Aku masuk begitu saja, tetapi Serge tidak menyumpahiku seperti biasanya. Dia duduk dengan tampang serius yang kukira tidak dimilikinya, mendengarkan radio.
Aku belum buka mulut sama sekali saat Serge mendahuluiku dengan memberi tahu, "Tembok W runtuh, anak bahlul. Kau bakal mati sebentar lagi. Atau jadi zombie."
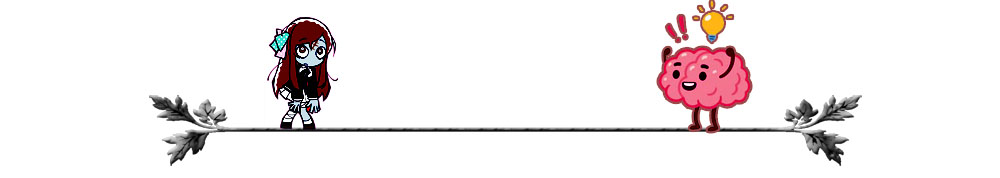
Pagi itu suasananya lebih tegang daripada biasanya. Berita penyerangan Duane diulang-ulang di radio. Beberapa kota merasakan dampak gempanya. Kami tidak merasakan apa-apa karena distrik kami sampai perbatasan barat laut yang paling jauh dari Duane dan perbatasan tenggara.
Selama beberapa jam, beberapa pakar berdebat siapa yang harus disalahkan.
"Kenapa Duane?" tanyaku ke piring roti di meja karena bertanya ke Serge akan membuatku kena darah tinggi. "Lubangnya, 'kan, di sini. Kok, pusat serangan zombie malah berseberangan?"
Serge mendengkus. "Ternyata kau masih punya otak untuk menyadarinya. Artinya, selama ini para zombie itu melakukan perjalanan panjang ke sana."
"Aku tidak bertanya padamu. Aku bertanya ke rotiku." Karena rotiku tidak menjawab, aku menggigitnya. "Benar kata mendiang Pak Radi. Orang-orang itu tololnya sampai ke tulang-tulang. Mau mengusir zombie malah mengundang lebih banyak lagi."
Serge, tak seperti biasanya, begitu pendiam pagi itu. Dia merenungi radio seperti orang patah hati, yang mana sangat aneh. Dia tidak mungkin bisa mematahkan apa yang tak dimilikinya.
"Kau pernah bilang kalau perbatasan itu justru paling aman, 'kan?" ungkitku. "Nah, sekarang saatnya membuktikan teori itu."
Serge mendadak menyengir, menampakkan gigi-giginya yang tidak rata dan kekuningan. Kulit keriput membuat wajah menyeringainya seram. Satu matanya yang picak dan memutih tampak kaku, tetapi mata yang satu lagi bergerak menatapku. Sepagian ini dia jarang bicara, tetapi sekarang matanya yang sehat berbinar-binar seperti anak kecil. Dia mulai terbahak dengan suara parau.
"Untuk saat ini—iya, perbatasan selain sisi tenggara, timur, dan selatan adalah yang paling aman." Dia membungkuk, meludah ke dalam gucinya, lalu tergelak lagi. "Tapi, begitu seisi tempat ini berubah jadi zombie, atau mayat tanpa otak korban para zombie—maka, mereka akan bergerak kemari juga!"
Aku mencecap rasa pahit teh. "Dan kenapa kau tertawa?"
"Karena aku sudah tua! Aku sebentar lagi mati! Kau yang masih muda ini akan menyaksikan dunia kiamat di depan matamu dan bertanya-tanya, 'Oh, Tuhan, mengapa aku tidak seberuntung Serge tua yang bijak—'"
Ucapannya terputus, digantikan gelak tawa yang makin nyaring saat aku melemparkan cangkir tehku ke atas kepalanya. Tentu saja dia menghindar seperti pesenam bertubuh lentur, seolah kulit kisut dan postur bungkuk serta anggota badan tak lengkap itu hanya kostum untuk menyembunyikan seorang gimnastik bertubuh luar biasa elastis di dalam sana.
"Bereskan ini, bocah bengal!" teriaknya, masih sambil cengengesan. "Aku akan mandi di sungai. Kusumpahi matamu berbisul dan pantatmu bintitan kalau berani mengintip!"
"Semoga kau tenggelam diseret arus, larut sampai muara sungai tenggara dan dipungut para zombie!" bentakku sementara Serge melompat keluar dari dapur sambil menjumput handuk yang tergantung di dinding.
Karena aku sering makan di sini, terpaksa aku membereskan dapurnya. Di meja, radio masih saja mengulang-ulang berita: debat antar tokoh politik, lempar-lemparan kesalahan antara Polisi Nusa dan Militer Nusa, proses pembangunan blokade baru di zona mati sekitar Duane, sampai iklan dan penyuluhan untuk bertahan hidup di tengah zombie. Kumatikan radionya karena bosan.
Setelah mengumpulkan beling di lantai, mataku menangkap sesuatu di balik papan kayu yang tersingkap di samping konter dapur Serge yang berjamur.
"Permisi," ocehku. Kucungkil papan yang mencuat dengan sudip, mengungkit sebuah relung di tanah yang tampaknya digali sendiri. Sebuah kotak berwarna perak seukuran kotak sepatu tersembunyi di sana.
Ini seperti harta karun. Bisa saja isinya majalah porno, foto memalukan si Serge tua, atau sesuatu yang berhubungan dengan aibnya. Maka, aku tidak menyia-nyiakan waktu. Aku membukanya.
Isinya memang foto-foto. Salah satu foto menunjukkan sederet pria yang diapit dua wanita di masing-masing kedua sisi, berpose seperti memamerkan otot lengan mereka. Meski sudah agak rusak dan menguning, senyum-senyum cerah itu masih terlihat. Mereka semua mengenakan seragam yang sama—merah-hitam. Pada foto lainnya, tampak seorang pria berambut cepak dengan otot lengan yang kencang dan rahang besar tengah merangkul seorang perempuan muda cantik dengan rambut sebahu. Keduanya lagi-lagi memakai seragam itu.
Aku lupa waktu. Aku masih duduk di sana, mengamati foto-foto dalam kotak perak, saat Serge muncul di belakangku.