Ada empat tipe zombie yang diresmikan secara tidak resmi oleh Serge; dari tipe 1 yang paling lamban karena mereka baru terinfeksi, tipe 2 yang mampu berburu manusia sedikit lebih baik, tipe 3 yang mulai memiliki kemampuan menalar, dan tipe 4 yang paling jarang ditemukan.
Batavia masih bersih dari zombie karena markas besar Polisi Nusa ada di sana. Kota-kota besar di sekitarnya seperti Radenal (markas kurirku), Renjani (rumahnya Ilyas), dan Larus hanya kebobolan beberapa zombie tipe 2 dan tipe 1. Namun, anggota PN di Renjani lumayan tanggap, jadi aku sama sekali tidak paham kenapa Ilyas bisa separanoid ini.
Bahkan, setelah beberapa zombie yang tadi berkumpul di depan rumahnya sudah diburu oleh anggota Polisi Nusa yang dia panggil sendiri, Ilyas masih ketar-ketir di depan pintunya.
Sekarang, dia mau keluar dari sangkarnya. Sudah 4 tahun dia tidak pernah keluar, katanya, padahal setahuku memang sejak anak-anak pun Ilyas tidak suka keluar rumah kecuali terpaksa. Yang lebih mencemaskanku adalah pandangan matanya yang kian liar dan tubuhnya yang bergetar hebat seolah dia baru saja menelan mesin motor yang masih menyala utuh-utuh.
Dia juga jadi lebih mudah marah. Aku tidak bisa salah senggol sedikit saja, dan suaranya langsung meninggi dengan tangannya yang bergerak-gerak jengkel.
Si nenek sesungguhnya sudah baikan, tetapi Ilyas bersikeras. Dia seperti menganggap kelalaiannya mengecek obat si nenek sebagai tindakan kriminal. Jadi, setelah mempersiapkan ini-itu, dan memastikan Emma kecil cukup tenang untuk ditinggal bersama si nenek, kami langsung berangkat ke dunia luar.
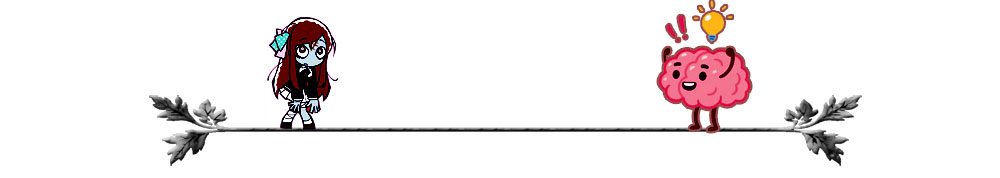
Yah, setidaknya kami mencoba langsung berangkat.
Tidak ada gunanya berlama-lama menguatkan diri di ambang pintu seperti ini karena hanya akan menyebabkan kita overthinking dan kian ragu hingga akhirnya batal keluar, tetapi Ilyas mengalami tremor parah. Aku mengira dia akan ambruk di atas rak sepatu. Kuberi tahu pemuda itu bahwa kami bisa saja keluar dengan santai dan balap karung sampai batas kota, dan kami tetap bakal lebih unggul dari para zombie lamban itu, tetapi dia seolah kehilangan fungsi pendengarannya.
"Kuncinya sudah dibuka sejak tadi," kataku. "Kita tinggal buka pintu dan lari."
Matanya masih menelaah pintu dengan bimbang, badannya maju-mundur antara hendak keluar atau berbalik. Dari wajah dan gerakan di lehernya, sepertinya dia mau muntah. Giginya mengapit kuku ibu jarinya dengan gelisah.
"Kalau kau mau," kataku lagi, "kita bisa ambil peti atau kotak kayu. Kau bisa masuk ke dalamnya sementara aku menyeret-nyeretmu ke apotek."
"Tolong," geramnya, "beri aku waktu sedikit lagi."
"Oke." Aku tersenyum, menunjukkan betapa pengertiannya aku.
Tiga detik kemudian, aku membuka pintunya.
"A—" Ilyas seperti akan pingsan di atas keset kaki, tetapi aku segera merenggut kerah bajunya dan menariknya keluar.
Masih ada zombie dari rumah seberang yang ditandai dengan garis polisi, tetapi ia tipe 1 yang lamban dan rabun. Aku masih sempat membuang karung sampah berisi zombie tipe 4 ke lahan kosong di ujung jalan, balik lagi untuk menutup pintu dan menguncinya dua kali, lalu menaruh kuncinya di kantong baju Ilyas karena pemuda itu masih membatu. Zombie-zombie itu tidak mengejar kami sama sekali.
Kuseret Ilyas bersamaku. Jalan sesepi ini efektif buat kami melenggang santai karena manusia yang berlarian panik seperti anak ayam disasar burung elang hanya akan membuat kericuhan dan menghalangi jalan.
"Lihat?" Aku menunjuk zombie-zombie di jalan. "Mereka ramah! Kau bisa saja berbaring di sini lima menit sementara menunggu mereka mencapaimu."
Ilyas tidak merespons. Ekspresi wajahnya lebih mirip mayat hidup. Lingkaran gelap di bawah matanya kian kentara di bawah cahaya matahari. Tatapannya liar ke sana kemari. Bahunya makin merosot dan langkahnya makin terseok.
Mendadak, pemuda itu jatuh ke tanah. Dia meringkuk, seperti mencoba menggulung dirinya sampai jadi bola dan tenggelam dalam tanah. Matanya mengamati zombie-zombie tipe 1 yang tidak melakukan apa-apa. Ilyas kemudian membungkuk ke atas parit dan muntah di sana. Tungkai dan sikunya gemetaran.
Aku berjongkok di sisinya. "Kalau ada PN yang kebetulan lewat, kau bakal dikira zombie." Kuperhatikan rumah-rumah bergaris polisi. "Dan, kita mesti bergerak sekarang. Zombie-zombie itu mulai sadar ada manusia karena suaramu."
Ilyas tersedak, lalu membuat suara mengeruk kasar dari kerongkongannya seolah dia sedang mencoba mengeluarkan paksa satu set alat pencernaan dari dalam perutnya ke parit. Kutarik ujung mantelnya dan kupakai untuk mengelap dagunya. Ilyas begitu lemas sampai-sampai dia menurut saja saat aku menariknya berdiri.
"Sudah, sudah." Kutepuk punggungnya dengan iba. Kubiarkan dia menyangga dirinya ke bahuku. "Aduh, siapa orang jahat yang membuatmu sampai seperti ini?"
Pemuda itu akhirnya menatapku. Tersengal, matanya menyorot nyalang. "Kau."
Perlahan tapi pasti, kami mulai melangkah maju dengan lenganku masih menyangganya. Ternyata Ilyas berat. "Zombie-zombie di lingkunganmu tidak berbahaya sama sekali, kok. Lihat! Yang berbahaya cuma zombie ganas tadi—dan aku sudah membuangnya untukmu."
"Karena kau yang membawa zombie ganas itu ke tempatku!"
"Nah, begitu dong!" Aku menyengir. "Yang semangat. Ayo, teriak lagi!"
Butir-butir peluh terbentuk di keningnya seperti orang demam. Rambutnya yang mengikal basah menempel ke sisi-sisi wajahnya.
"Semua zombie di sini tipe 1." Aku memberitahunya sambil menunjuk zombie-zombie yang bengong di dalam halaman rumah yang bergaris polisi. "Bentuk mereka bikin jijik, jadi usahakan untuk tidak terlalu memandangi borok mereka."
Ilyas mengeluarkan suara berdeguk yang membuat punggungku merinding.
"Kalau kau memuntahiku lagi, kutendang anumu."
"Aku tidak mengerti ..." gumamnya seraya menatap zombie-zombie di balik garis polisi yang melintangi rumah-rumah kosong. "Zombie-zombie ini ... mereka bukan penghuni rumah ini. Mereka bukan tetanggaku."
Aku mengerutkan wajah. "Dengan luka-luka di wajah mereka, kau masih bisa mengenali tetanggamu?"
Pemuda itu mengangguk. Wajahnya masih pucat, tetapi dia tetap berusaha mengamati zombie-zombie di sekitar kami. "Perempuan itu ...." Telunjuknya menuding satu zombie wanita paruh baya yang telinganya peretel, hidungnya hanya berupa gumpalan kemerahan, dan mulutnya menganga dengan tatapan menerawang ke langit. "Dia penghuni rumah blok sebelah, bukan rumah yang ini. Barangkali, ia adalah salah satu dari enam zombie yang tadi berkerumun di depan rumahku."
Aku mengerjap. "Terus?"
"Terus," lanjutnya jengkel, "itu artinya PN tidak membereskan mereka. Polisi yang kuhubungi cuma menggiring zombie-zombie ini ke rumah yang sudah tidak berpenghuni dan pergi begitu saja seperti polisi pemalas lainnya!"
Aku mengerutkan bibir dan menimbang-nimbang di mana salahnya para polisi itu. "Begini, ya, Ilyas, kau mungkin jarang keluar rumah, makanya tidak tahu. Zombie tipe 1 tidak bisa dibunuh. Atau lebih tepatnya, susah banget dibunuh. Mereka mesti dicincang sampai halus, lalu dibakar. Kalau tidak, bagian tubuh mereka masih bisa bergerak. Kecuali fakta bahwa mereka juga bisa menginfeksi lewat gigitan, tipe 1 tidak berbahaya karena mereka lamban, rabun, dan lemahnya minta ampun. Jadi, kurasa polisi-polisi itu sudah benar. Mereka mengekang tipe 1 ini di balik garis polisi dan menunggu setidaknya sampai seminggu sampai zombie-zombie ini naik pangkat jadi tipe 2 agar lebih gampang dimusnahkan."
Ilyas mengernyitkan alisnya. "Tidak pernah ada pengklasifikasian tipe-tipe macam itu dalam penyuluhan—"
"Oh, sori. Itu cuma klasifikasi pribadi, dipatenkan Serge & Cal Company. PN cuma membaginya ke tiga kategori: 'manusia terinfeksi' alias yang masih dalam masa inkubasi 6 jam, 'zombie baru' yang susah dibunuh, dan 'zombie biasa' yang lebih mudah dimusnahkan setelah 7 hari. Intinya, zombie-zombie baru ini memang lebih baik dibiarkan saja karena mencoba memusnahkan mereka itu percuma."
Ilyas menyeka hidungnya dengan punggung tangan. "Bisa beri tahu aku tipe-tipe zombie yang kau klasifikasikan sendiri itu?"
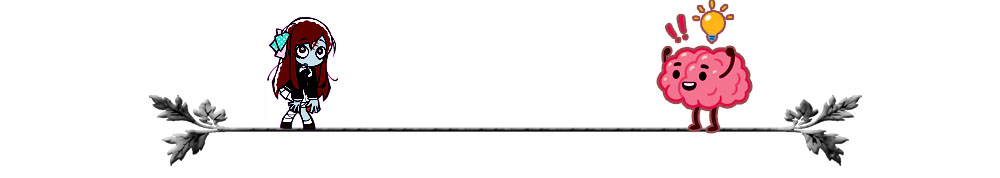
Kami tiba di apotek saat petang. Langit sudah oranye, bayang-bayang pepohonan jatuh ke jalanan, kertas-kertas poster beterbangan. Rumah-rumah yang masih berpenghuni mulai menyalakan pencahayaan redup. Beberapa polisi patroli sempat menghampiri kami, tetapi mundur lagi saat aku mengangkat kartu ID kurirku. Ilyas sendiri hanya mengekor dengan manisnya, jadi dia tidak begitu menarik perhatian.
Apotek itu sudah diberi garis polisi. Di dalamnya, seorang wanita terkapar di belakang etalase kaca dengan kepala menganga. Sisa-sisa mengerikan meleleh keluar membasahi rambutnya.
Yah, kurasa Ilyas benar—meski Polisi Nusa di sini tanggap terhadap panggilan, tetapi mereka malas membersihkan korban. Namun, tetap saja aku memahami keputusan mereka. Mereka tidak mungkin melakukan pembakaran mayatnya di sini, petugas kremasi butuh waktu untuk memenuhi panggilan, dan seharusnya garis polisi sudah cukup menghentikan orang-orang idiot dari memasuki bangunan terinfeksi. Bahkan, walau perempuan ini jadi zombie, selama tidak ada manusia di dekatnya, dia takkan melakukan apa-apa selain bengong.
"Ugh, otaknya—" Ilyas tercekat. Dia menarik kerah mantelnya untuk menutupi hidung. Matanya berair. "Otaknya masih ada. Kau yakin dia tidak akan berubah? Ini hampir 6 jam sejak kau melihat zombie ganas tadi keluar dari sini, 'kan?"
"Betulkah? Kalau begitu, kita mesti cepat." Kutarik Ilyas mengikutiku ke belakang etalase. "Ambil obatnya. Kalau bisa, setelah ini kita lari mati-matian."
Ilyas mulai bergerak. Dia mencari dan menjumputi kotak-kotak obat dengan cepat. Gerakannya efisien sekali, padahal aku sempat curiga dia bakal menjatuhkan barang-barang dengan jari-jari panjang yang gemetaran itu.
"Aku tidak percaya aku bisa keluar rumah hari ini," gumamnya pelan. "Maksudku ... benar-benar keluar, menginjak tanah, bukannya berdiri di balkon untuk menjemur Emma."
"Apa kau menggantung adikmu di tali dan menjepitnya pakai jepitan jemuran?"
Untuk kali itu, entah dengan alasan apa dia memutuskan untuk mengabaikan ejekanku. Senyumnya mengembang, tipis saja, tetapi sorot matanya begitu hangat. "Aku ... kurasa sekarang aku bisa jadi sedikit lebih berani. Trims, Cal."
Otakku seperti korslet. Kudapati diriku memasang senyum genit dan tersipu sendiri. Aku buru-buru berbalik dan menepisnya dengan lambaian tangan. "Ah, tidak perlu sampai seperti itu."
Keluar dari apotek, aku masih memegangi ranselku yang menggembung penuh kotak obat di tangan kiri dan menyiagakan samurai di tangan kanan. Kertas-kertas poster di jalanan tertiup angin sore, melintas ke samping kakiku, menempel di lutut Ilyas, lalu salah satunya menemplok ke wajahku, menutupi sebelah mataku.
"Ilyas," kataku, menghadap ke arahnya dan memperlihatkan kedua tanganku yang penuh. "Tolong."
Pemuda itu membungkuk, tetapi tidak langsung menyingkirkan poster sialan ini. Dia berjengit mengamati poster di mukaku. "Kebijakan perekrutan PN tidak masuk akal. Mereka bahkan tidak lagi mewajibkan pendidikan di akademi kepolisian."
"Lebih tidak masuk akal lagi orang yang membaca poster yang masih menempel ke muka temannya tanpa menyingkirkannya lebih dulu."
"Sori." Dia meraih poster itu dan membacanya. "Kenapa kau tidak masuk kepolisian saja, Cal? Pasti gampang sekali buatmu membantai zombie seharian."
Aku mendengkus dongkol. "Malas! Lebih baik jadi kurir!"
Pemuda itu mengangkat alis, menyadari sesuatu. "Oh, syarat tinggi badan—"
"Jangan bawa-bawa ukuran badan!" Kuselempangkan ransel di satu bahu. "Lagi pula, kurir sama baiknya dengan PN! Kami sama-sama digaris depan empat tahun belakangan ini. Bandingkan dengan organisasi militer yang tidak ada gunanya!"
"Karena mereka dibubarkan," ujarnya.
"Untuk alasan yang bagus," kataku. "Gara-gara mereka, Tembok W sisi tenggara kebobolan. Zombie dari Neraka sana bocor ke Nusa."
"Kurasa, tidak masuk akal melimpahkan semua kesalahan ke satu pihak saja." Ilyas mengerutkan alisnya lagi. Sepertinya, segala hal tidak masuk akal buat cowok ini. "Setelah 70 tahun Kesatuan Pengendali dan Pemberantas Zombie dibubarkan, kelompok itu tiba-tiba dibentuk kembali 4 tahun lalu—hanya dalam semalam. KPPZ tahun 2097, tidak mungkin disamakan dengan KPPZ generasi baru 4 tahun lalu—harusnya semua pihak sadar itu. Mustahil cuma Organisasi Militer Nusa yang salah. Semua pihak—para menteri, presiden sendiri, dan badan kepolisian—yang menyetujuinya berbagi kesalahan itu, tetapi mereka tidak bisa membubarkan semua orang. Setelah saling tunjuk hidung, satu-satunya pilihan hanya membuat suara bulat tentang kambing hitamnya. Tentu saja mereka menunjuk organisasi militer."
Aku memutar bola mata. "Soalnya anggota militer yang paling banyak direkrut dadakan ke dalam KPPZ 4 tahun lalu, dan mereka juga yang menutup-nutupi masalah lubang di tembok tiap satu dekade, jadi mereka yang salah. Titik."
Ilyas berhenti melangkah di belakangku. "Dari mana kau tahu semua itu?"
Aku ikut berhenti. Mataku mengerjap-ngerjap. "Ada di berita—"