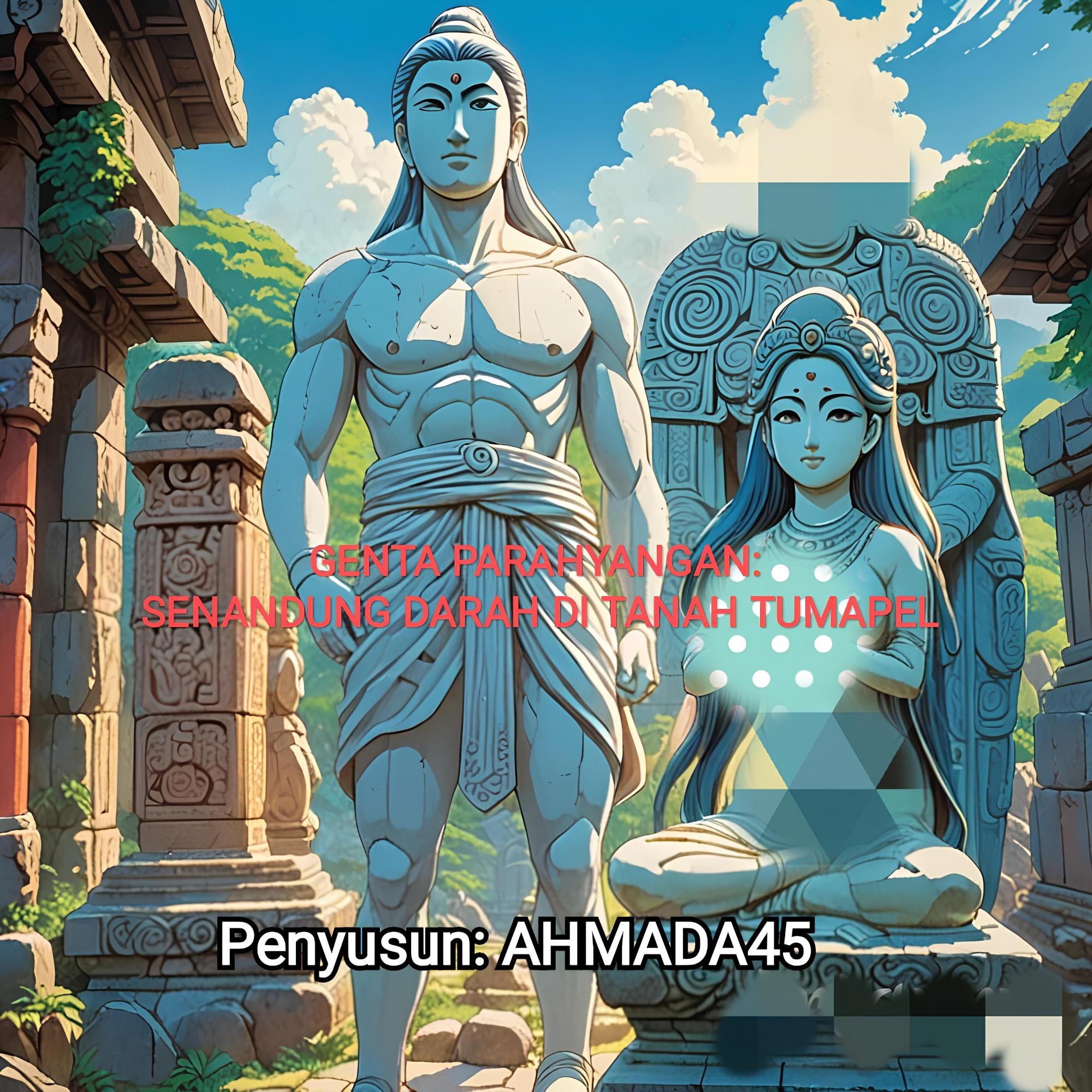
1.1 Mata Elang di Atas Lara
Senja merayap turun di atas tanah Tumapel laksana selubung duka raksasa yang diembuskan perlahan dari puncak-puncak gunung. Ini bukan senja yang dikenal para pujangga, bukan selendang jingga keemasan yang memeluk bumi dengan hangat sebelum tidur. Langit di atas lembah yang subur itu tampak kelabu pasi, sakit, seolah-olah Sang Hyang Surya sendiri enggan memantulkan keindahan bagi sebuah negeri yang tengah dirundung lara. Warna-warni cemerlang itu seakan terserap habis oleh selaput kesedihan yang tak kasat mata, menyisakan gradasi muram yang membebani pandangan dan menekan perasaan.
Angin yang biasanya berhembus dari puncak Gunung Kawi, membawa kesejukan murni dan aroma kembang hutan, kini terasa berbeda. Hembusannya tidak lagi menyegarkan, melainkan membawa desah panjang penderitaan ribuan jiwa. Ia seperti suara gaib yang menyapu lembah, membisikkan keluh kesah para petani yang punggungnya patah oleh beban kerja dan hati yang remuk oleh perampasan. Ia membawa aroma keringat bercampur air mata, bau tanah yang basah bukan oleh hujan berkah, melainkan oleh tumpahan darah sia-sia. Di padukuhan-padukuhan yang tersebar seperti butiran jagung di telapak tangan dewa, dari Jatiwangi hingga Pangkur, pintu-pintu kayu yang berat ditutup lebih cepat dari biasanya. Orang-orang tidak lagi duduk-duduk di beranda, berbagi cerita atau canda. Keheningan yang cemas menggantikan keriuhan ramah-tamah. Bahkan api di dapur-dapur seolah menyala dengan enggan, cahayanya redup, seolah takut menarik perhatian yang tak diinginkan. Kehidupan memang masih berjalan—sawah masih dibajak, ternak masih digembala, pasar masih dibuka—namun gairahnya telah padam. Roda kehidupan berputar karena terpaksa, bukan karena harapan. Orang-orang masih tertawa sesekali, tetapi tawa mereka hampa, hanya getar suara tanpa sukacita, sebuah kebiasaan lama yang kehilangan maknanya.
Tinggi di atas semua itu, di lereng gunung yang terjal dan nyaris tak pernah dijamah telapak kaki manusia, berdirilah sesosok tubuh. Ia berdiri di antara bebatuan padas raksasa yang membisu, saksi agung dari ribuan musim yang telah berlalu. Tubuhnya tegap, kokoh, dan diam membatu, seolah ia sendiri adalah bagian dari geologi purba gunung itu. Angin senja yang menggigit memainkan ujung kain panjang berwarna hitam yang melilit kepalanya, sesekali mengibarkan rambutnya yang hitam legam dan sedikit ikal, membebaskannya dari ikatan untuk sesaat sebelum kembali menjatuhkannya. Wajahnya, dengan garis-garis tegas yang seolah dipahat dari batu pualam oleh tangan seorang seniman dewa, tidak menampakkan getar perasaan apa pun. Datar, dingin, dan tak terbaca.
Namun, jika ada yang berani menatap matanya, mereka akan melihat sebuah dunia yang berbeda. Sepasang mata itu, tajam laksana mata elang gunung yang mengawasi mangsanya dari ketinggian, menyiratkan gejolak seribu badai. Di dalam manik hitamnya yang pekat, berkecamuk amarah, kesedihan, dan sebuah pertanyaan besar yang tak kunjung menemukan jawaban. Sorot mata itu menatap jauh ke bawah, menembus lapisan kabut tipis yang mulai terbentuk, tertuju pada kerlip-kerlip lampu minyak yang satu per satu menyala di Padukuhan Jatiwangi. Sebuah titik kecil, setitik debu dalam hamparan kekuasaan Tumapel yang luas, namun bagi pemuda itu, titik cahaya tersebut adalah pusat dari segala kegelisahannya malam ini.
Pemuda itu bernama Arok.
Namanya tidak akan pernah disebut dalam pasamuan agung di pendopo kadipaten. Para bangsawan yang bergelimang sutra dan emas tidak mengenalnya, atau mungkin memilih untuk tidak mengenalnya. Namanya adalah legenda yang berbeda, legenda yang lahir dari bayang-bayang dan bisik-bisik. Bagi para prajurit Tumapel yang bertugas merampas upeti, nama Arok adalah desis ketakutan di malam hari, hantu gunung yang bisa muncul dari ketiadaan dan lenyap tanpa jejak, meninggalkan mereka dengan tangan hampa dan rasa malu yang membakar. Bagi kaum papa yang lidahnya telah kelu untuk sekadar mengeluh, yang suaranya telah habis untuk memohon, nama Arok adalah secercah harapan. Ia adalah cerita yang dibisikkan seorang ibu kepada anaknya yang kelaparan, bahwa "Sang Bayangan Kawi" akan datang mengembalikan beras mereka. Bagi penguasa, bagi Akuwu Tunggul Ametung dan para bekelnya, ia adalah durjana, kepala gerombolan perampok liar yang mengganggu ketertiban, sebuah borok yang harus ditumpas hingga ke akarnya. Namun bagi mereka yang pernah merasakan langsung pertolongannya—sebuah karung gabah yang muncul di depan pintu saat fajar, atau sekelompok prajurit pemeras yang ditemukan terikat tak berdaya di tepi hutan—ia adalah titisan dewa penolong yang turun ke bumi, jawaban atas doa-doa mereka yang paling putus asa.
Tangannya yang besar dan kokoh, dengan jari-jari yang kapalan karena terlalu sering menggenggam gagang senjata dan memanjat tebing batu, terkepal erat di sisi tubuhnya. Begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Urat-urat di lengannya, yang sekeras dan selentur dahan pohon jati tua, menegang, memetakan jaringan kekuatan yang terpendam di bawah kulitnya yang sawo matang. Setiap kali ia memandang padukuhan di bawah sana, dadanya terasa sesak. Bukan karena dinginnya udara pegunungan yang menipis, tetapi oleh hawa panas amarah yang terus membara di dalam sanubarinya, sebuah api abadi yang disulut oleh ketidakadilan yang dilihatnya setiap hari.
Di dalam benaknya, pemandangan lembah itu bukanlah sekadar titik-titik cahaya. Ia melihatnya dengan lebih jelas, lebih menyakitkan. Ia melihat wajah Pak Suro, seorang petani tua di ujung padukuhan, yang dua pekan lalu ia lihat dipukuli hingga tersungkur ke tanah berlumpur hanya karena mencoba menyembunyikan seikat kecil padi untuk cucunya yang sakit. Para prajurit tertawa saat merampas ikatan padi itu, menyebutnya upeti tambahan atas "ketidakjujuran". Arok melihat wajah Laras, cucu Pak Suro, yang menatap dengan mata besar penuh ketakutan dan kebingungan, tidak mengerti mengapa kakeknya yang baik hati diperlakukan seperti binatang.
Kenangan itu membakar. Arok bisa merasakan kembali getaran tanah saat tubuh renta Pak Suro terbanting. Ia bisa mendengar kembali tawa angkuh para prajurit, suara yang lebih melukai daripada pukulan itu sendiri. Dan ia bisa merasakan ketidakberdayaannya saat itu, saat ia hanya bisa mengamati dari kejauhan, mengepalkan tinjunya di dalam semak-semak, menahan diri untuk tidak melompat keluar dan membantai mereka semua di tempat. Tanca yang menahannya, membisikkan bahwa waktu dan tempatnya salah, bahwa kematian mereka hanya akan membawa bencana yang lebih besar bagi seluruh padukuhan. Saat itu Arok patuh, namun kepatuhan itu meninggalkan luka di jiwanya.
Malam harinya, ia dan orang-orangnya mencegat rombongan itu di kelokan hutan yang sepi. Mereka tidak membunuh, sesuai prinsip yang selalu ia pegang. Mereka hanya melumpuhkan, mengambil kembali semua hasil rampasan, dan meninggalkan pemimpin prajurit itu terikat di pohon dengan pesan yang terukir di tanah: "GUNUNG MENGAWASI". Ia tahu, karung-karung beras yang ia kembalikan secara diam-diam ke lumbung desa, termasuk ke depan gubuk Pak Suro, adalah bantuan nyata. Namun itu tidak menghapus citra wajah Laras yang ketakutan atau ringis kesakitan Pak Suro. Bantuan itu terasa seperti menambal luka menganga dengan sehelai daun.
Itulah yang membuatnya marah. Ia melihat kehidupan yang seharusnya damai dan tenteram, kini dipagari oleh ketakutan yang pekat. Ia mendengar jerit yang tak bersuara dari para petani yang hasil panennya dirampas atas nama upeti, sebuah kata yang telah kehilangan makna sucinya dan berubah menjadi sinonim dari perampokan yang dilegalkan. Ia merasakan getar bumi di bawah kakinya, dan ia bersumpah getaran itu adalah tangisan Ibu Pertiwi yang lelah karena terus-menerus dibasahi oleh air mata dan darah orang-orang tak berdosa.
Siapakah yang bersalah atas semua ini? Arok tahu jawabannya. Sumber dari segala penderitaan ini bermuara pada satu nama: Tunggul Ametung. Sang Akuwu Tumapel. Seorang penguasa yang duduk di singgasana gadingnya yang megah, perutnya kenyang oleh hasil bumi terbaik, tubuhnya hangat oleh selimut sutra, telinganya tuli oleh puji-pujian para penjilat. Ia memerintah bukan dengan wibawa, tetapi dengan pedang. Ia membangun kemegahan istananya bukan dengan keringatnya, tetapi dengan air mata rakyatnya. Ia adalah akar dari pohon beracun yang dahannya menjalar ke seluruh penjuru negeri, dan para bekel serta prajuritnya adalah buah-buah beracun yang mencekik siapa saja yang berada di bawahnya.
Arok sering bertanya pada keheningan malam, pada bintang-bintang yang berkedip acuh tak acuh di atas sana. Di manakah keadilan Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat semua ini dari kahyangan? Apakah Siwa, sang pelebur, tidak murka melihat ketidakseimbangan ini? Ataukah Tuhan Maha Pencipta, sang pemelihara, tidak peduli pada ciptaanNya yang menderita? Atau jangan-jangan, Tuhan Yang Maha Pengasih, welas asih memang telah meninggalkan tanah ini, membiarkannya membusuk dalam kezalimannya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, kadang membuatnya merasa kecil dan tak berarti, kadang justru menyulut keyakinan baru: jika takdir justru tak berubah, diam, maka manusialah yang harus bergerak. Jika takdir enggan berpihak pada yang lemah, maka takdir harus dipaksa, dibengkokkan dengan tangan-tangan yang berani.
Ia menarik napas dalam-dalam. Udara gunung yang tajam dan dingin memenuhi paru-parunya, sedikit mendinginkan api yang berkobar di dadanya, mengubahnya dari amarah yang membabi buta menjadi baja yang dingin dan fokus. Ia bukan lagi sekadar pemuda desa yang marah karena ketidakadilan. Tahun-tahun yang ia habiskan hidup di alam liar, belajar dari alam, dari Tanca yang bijaksana, dan dari kerasnya perjuangan untuk bertahan hidup, telah menempanya menjadi sesuatu yang lebih. Ia belajar membaca jejak seperti binatang buas, bergerak tanpa suara seperti kabut, dan berpikir beberapa langkah ke depan seperti seorang ahli catur.
Pandangannya kembali tertuju pada kerlip lampu di Jatiwangi. Malam ini, Ki Glondong Wisesa, salah satu anjing penjilat Tunggul Ametung yang paling rakus, berada di sana. Berita telah sampai kepadanya melalui jaring-jaring informannya—para pedagang kecil, gembala, dan pemburu yang membenci para penguasa sama seperti dirinya. Ki Glondong dan pengawalnya baru saja selesai "menginspeksi" lumbung desa, merampas hampir seluruh isinya dengan dalih tunggakan pajak dari musim tanam yang gagal. Kini mereka tengah berpesta di rumah kepala desa, yang terpaksa menjamu mereka dengan senyum ketakutan, menyajikan sisa-sisa hasil bumi dari rakyatnya sendiri kepada para perampasnya.
Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat dan tanpa kehangatan, tersungging di bibir Arok. Ini adalah kesempatan. Bukan hanya untuk mengembalikan apa yang telah dirampas, tetapi untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan bergema jauh melampaui batas-batas Padukuhan Jatiwangi. Bukan sekadar aksi seorang perampok, tetapi pernyataan seorang pejuang.
Mata elang itu kini menyipit. Badai di dalamnya telah mereda, berganti menjadi ketenangan yang mematikan, ketenangan sebelum sambaran petir. Ia telah selesai merenung. Ia telah selesai bertanya. Malam ini adalah malam untuk bertindak. Ia tidak akan lagi menjadi bayangan yang hanya bereaksi. Malam ini, ia akan menjadi tangan takdir itu sendiri. Dari puncak kesunyiannya, ia akan turun ke lembah yang berduka. Bukan sebagai dewa, bukan sebagai durjana, tetapi sebagai Arok. Dan itu, untuk saat ini, sudah lebih dari cukup.
***
1.2 Bara, Nalar, dan Wibawa
Di belakang Arok, dari celah sebuah gua yang tersembunyi sempurna di balik jalinan akar-akar raksasa pohon randu alas, beberapa bayangan bergerak mendekat. Pintu gua itu bukanlah sekadar lubang di dinding batu; ia adalah mulut bumi yang berjanggut akar, tersembunyi oleh tirai lumut dan sulur-sulur liar, mustahil ditemukan oleh mata yang tidak tahu di mana harus mencari. Dari luar, yang terdengar hanyalah desau angin dan gemerisik daun. Namun dari dalam, tercium aroma samar kayu bakar, minyak kelapa untuk merawat senjata, dan ramuan obat-obatan dari dedaunan hutan.
Mereka adalah orang-orangnya, jiwa-jiwa yang tersingkirkan oleh tatanan yang zalim. Di antara mereka ada mantan petani yang tanahnya dirampas, bekas prajurit rendahan yang muak dengan perintah keji atasannya, pedagang yang bangkrut karena pungutan liar, dan pemuda-pemuda yang memilih hidup di alam liar daripada harus menundukkan kepala di bawah telapak kaki para pemeras. Wajah mereka keras, ditempa oleh terik matahari, dinginnya malam, dan perjuangan hidup yang tak kenal ampun. Namun di balik kekerasan itu, mata mereka menyimpan sesuatu yang langka di tanah Tumapel: kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kesetiaan itu tidak lahir dari rasa takut atau iming-iming harta, tetapi dari rasa hormat yang tulus pada pemuda yang kini berdiri seperti arca di bibir tebing itu. Mereka melihat di dalam diri Arok bukan hanya seorang pemimpin yang kuat, tetapi cerminan dari kemarahan dan harapan mereka sendiri.
Salah seorang dari mereka, seorang lelaki paruh baya yang gerakannya paling tenang dan berwibawa, melangkah maju meninggalkan kehangatan api unggun di pusat gua. Namanya Tanca. Cambangnya yang lebat telah mulai dihiasi uban, jejak waktu dan beban pikiran, namun tubuhnya masih kekar laksana banteng lading, sisa-sisa kekuatan masa mudanya yang belum luntur. Langkahnya mantap, nyaris tak bersuara di atas tanah berbatu, kebiasaan yang ia kembangkan selama bertahun-tahun hidup dalam persembunyian. Tanca bukan sekadar yang tertua; ia adalah sauh bagi gerombolan itu, penasihat Arok yang paling dipercaya. Dahulu, ia adalah seorang demang di sebuah padukuhan kecil yang makmur, dihormati karena kearifannya. Namun kearifan itu pula yang membuatnya terusir, setelah ia dengan berani menyuarakan keberatan atas kenaikan upeti yang tak masuk akal di hadapan utusan Akuwu. Ia kehilangan jabatan, tanah, dan kehormatannya di mata penguasa, namun ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga: kebebasan untuk tidak menjadi penjilat.
Tanca berhenti beberapa langkah di belakang Arok, memberinya ruang, namun kehadirannya terasa. Ia bisa merasakan kekakuan di pundak pemimpin mudanya itu, getaran amarah yang tertahan yang seolah memancarkan panas di udara yang dingin.
“Angin malam semakin dingin, Arok,” desis Tanca pelan, suaranya serak namun dalam, seperti gema dari dasar sumur. Itu bukan sekadar pernyataan tentang cuaca. Itu adalah sebuah nasihat. “Tidak baik berlama-lama di tempat terbuka seperti ini. Kemarahan yang terlalu lama dipendam di hawa dingin bisa membekukan hati, mengubahnya menjadi batu dendam yang keras dan rapuh.”
Arok tidak bergeming untuk sesaat. Pandangannya masih terpaku pada titik-titik cahaya di lembah, seolah mencoba menyerap semua penderitaan dari kejauhan. "Dinginnya angin ini tidak seberapa dibanding dinginnya hati orang-orang di bawah sana, Paman Tanca," jawabnya tanpa menoleh. Suaranya rendah, bergetar. "Mereka hidup, tapi jiwa mereka mati membeku. Setiap hari mereka bangun dengan rasa takut, bekerja dengan keputusasaan, dan tidur dengan perut lapar. Kita di sini, di atas gunung, setidaknya masih memiliki kebebasan dan kehangatan dari api kita sendiri. Mereka? Api di dapur mereka pun seolah tak sanggup menghangatkan harapan."
Tanca menghela napas panjang, kepulan uap putih keluar dari mulutnya dan lenyap di telan kegelapan. Ia sudah menduga arah pembicaraan ini. Gejolak di dada Arok adalah gunung berapi yang terus-menerus bergolak, dan Tanca selalu berusaha menjadi katup pengamannya. “Kita sudah melakukan apa yang kita bisa, Ngger. Kita bukan sekadar bersembunyi. Kita menyerang saat perlu, kita menolong saat mampu. Mengambil kembali sebagian upeti, membagikannya pada janda-janda dan anak yatim, menakuti para pemungut pajak rendahan agar tidak terlalu semena-mena. Tapi kita harus sadar akan kekuatan kita. Kita ini hanya sekelompok kecil, setitik kerikil di hadapan gunung kekuasaan Tumapel. Kita bukan dewa yang bisa menghapus semua penderitaan di tanah ini dengan satu sapuan tangan.”