Gemah ripah loh jinawi adalah bahasa yang luar biasa, yang menggambarkan kesuburan negeri kita. Alam yang dianugerahkan Allah begitu gemah ripah loh jinawi untuk mereka. Allah memerintahkan agar rakyat negeri ini senantiasa tata tentrem kerta raharja. Semuanya harus tenteram, di mana pun di seluruh pelosok negeri.
Makna dari kerta raharja adalah mapan. Sejahtera. Bisa makan, bisa menyekolahkan anak, tidak kekurangan sesuatu apa pun, dan damai. Tata tentrem kerta raharja adalah bahasa Jawa, yang dalam bahasa Indonesia berarti adil dan makmur.
Di zaman reformasi ini ada istilah “Masyarakat Madani”. Dalam Islam namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr. Gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja, masyarakat adil dan makmur, dalam Islam disebut baldatun thayyibatun. Sudah, itu saja. Tapi, Allah menambahkan wa rabbun ghafûr. Maksudnya, kaya atau miskin bukan masalah, asal hatinya tidak bimbang. Asal tetap bersyukur. Misalnya hidup rukun, tenteram, dan raharja, yang semua itu diterima oleh Allah. Jangan sampai ada satu pun yang tidak diterima Allah. Karena itu, ada bahasa wa rabbun ghafûr.
Kalau dipikir-pikir, tata tentrem kerta raharja itu bukan hanya yang bagus-bagus. Orang bermain judi juga rukun. Bandar dan yang main rukun. Itu namanya kerta raharja, tapi tidak wa rabbun ghafûr. Main di tempat prostitusi itu tata tentrem kerta raharja, tapi tidak rabbun ghafûr. Tidak diterima Gusti Allah. Jadi, tidak cukup hanya tata tentrem kerta raharja. Kita juga harus ingat jika kesenangan seperti itu, ketenteraman seperti itu, bersalah pada Gusti Allah.
Jadi, yang harus dijadikan pedoman itu adalah bagaimana caranya bisa makan, tidak sampai kelaparan, tapi jangan sampai Allah marah. Mau jadi lurah, mau jadi bandar judi, mau jadi tukang ojek, tidak masalah. Namun kita harus tetap ingat; apakah yang kita lakukan diterima sama Gusti Allah atau tidak?
Kalau sampai Allah tidak mengampuni apa yang kita lakukan, kasihan anak kita, kasihan cucu kita, kasihan keluarga kita. Jadi sebaiknya, dalam memilih pekerjaan kita juga harus mempertimbangkan bagaimana agar pekerjaan kita diterima Gusti Allah. Jangan sampai ada perilaku kita yang bisa menyebabkan Allah murka. Bagi saya, pedoman utama dalam hidup itu hanya wa rabbun ghafûr.

Kalau pekerjaan kita memerah susu sapi, ya tidak ada masalah, mesti rabbun ghafûr. Tapi kalau kita berjudi, baik main kartu ataupun dadu, itu bisa membuat Allah marah.
Sawang sinawang (saling memandang) juga tidak asal pandang. Nyawang (memandang) suami atau istri orang, itu juga tidak bagus. Maksud sawang sinawang bukan memandang rupa atau fisik, tapi memandang untuk belajar, mempelajari yang baik-baik dari orang lain. Itu namanya belajar.

Belajar beda dengan sekolah. Saya tidak sekolah, tapi saya belajar. Belajar dari hidup. Sekolah tidak menjamin orang belajar dan berbuat baik. Saya tidak sekolah tapi tidak korupsi. Sementara kebanyakan orang yang korupsi itu tamatan sekolah. Kalau kita mau korupsi, korupsi apa? Kita tidak pernah dilewati uang. Dilewati cuma sedikit, alhamdulillah. Kalau kita dilewati uang melalui seseorang, kita berterima kasih kepada orang itu. Kepada yang memberi, Gusti Allah, kita bersyukur. Jadi, diberi apa pun oleh Allah, biar uang yang hanya lewat dan sedikit, kita harus bersyukur.
Kalau kamu orang Jawa, jangan sampai kehilangan Jawanya. Menurut saya, lebih baik orang yang mengaji dengan hati yang suci, meski kemampuan melagukan Arab dan tajwidnya jelek. Yang penting hati bersungguh-sungguh. Tidak ada orang yang membaca Al-Quran dengan bagus. Membaca Al-Quran itu soal ikhlas atau tidak ikhlas.
Mengaji tidak harus dilagukan deng an cara Arab. Menggunakan lagu Jawa juga boleh. Sepertinya Gusti Allah lebih senang kalau orang Jawa mengaji dengan lagu Jawa. Tidak masalah mengaji dengan lagu Jawa, yang penting dalam hatinya bersungguh-sungguh ingin mengaji. Yang penting bersungguh-sungguh, jujur, tidak pernah berbohong pada siapa pun, beres, pasti mendapatkan surga.
Yang sudah sembahyang tidak boleh sombong pada yang belum sembahyang. Orang kaya tidak boleh sombong pada yang miskin. Orang pintar jangan membodoh-bodohkan orang lain. Pokoknya, tidak usah sombong. Orang alim, yang sudah jadi ustadz, apalagi, tidak boleh sombong.
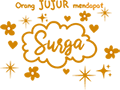
Kadang, ada yang memanggil saya kiai haji. Saya senang, tapi nelangsa juga. Biasanya saya dipanggil seperti itu di acara pengajian. Saya dipanggil kiai karena melihat pakaian saya, baju takwa dan berpeci. Baju takwa dan peci saya sudah dianggap sebagai baju kiai.
Padahal, saya berpenampilan seperti itu karena saya sungkan sama tamu-tamu pengajian. Saya hanya mencoba untuk menghormati semua yang datang di pengajian. Saya berpakaian seperti itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Tidak ada hubungannya dengan kiai. Tidak ada hubungannya dengan ustadz. Orang ini baju dari Tiongkok.
Zaman dahulu, untuk bisa menjadi seorang kiai, syaratnya harus membaur dengan umat. Karena itu, pakaiannya tidak boleh beda dengan pakaian rakyat jelata. Jadi, di desa-desa zaman dulu, kiai itu kalau bisa mencari rumput, ya, cari rumput. Kalau bisa menggembala sapi, ya, menggembala. Membawa cangkul, berkalung sabit, bercelana pendek, tidak masalah. Begitulah kiai zaman dulu.
Tapi, kalau malam mereka mengajar ngaji. Bukan lantaran mengajarkan mengaji lantas bajunya harus beda. Kiai yang baik itu yang pakaiannya tidak beda dengan orang kebanyakan. Lha wong tugas kiai menemani banyak orang. Kalau pakaiannya lebih mewah daripada kebanyakan orang, sulit untuk membaur, ‘kan? Kiai itu harus mau, misalnya, jongkok bareng orang lain yang jongkok.
Dulu di tahun 1970-an, baju takwa seperti yang banyak orang pakai sekarang ini, kalau di Jawa, ibaratnya baju ludruk (kesenian khas Jawa Timuran berupa drama yang diselingi kidung dan tarian—ed.). Setiap ada pertunjukan “ludruk”, semua orang memakai pakaian takwa, lengan panjang, lalu berjoget. Lha kok sekarang diidentikkan dengan kiai.
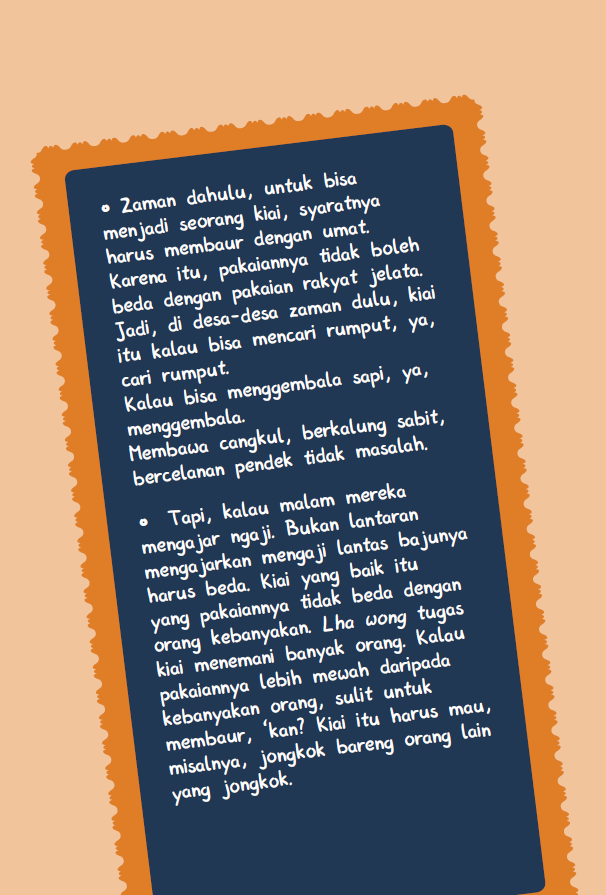
Kiai selalu memakai baju koko. Baju koko itu sebenarnya baju Tionghoa, lantas “diklaim” ustadz dan dinamai “baju takwa”. Bagaimana coba bisa seperti itu? Pakaian itu tidak menggambarkan kelakuan, malah bisa-bisa membohongi. Jangan gampang percaya dengan hal-hal yang terlihat. Jangan tertipu penglihatan kita. Semuanya harus “dirasakan” dulu. Kalau orang Jawa punya ilmu, yang matanya bisa tahu mana yang bohong, mana yang tidak. Dari urat-urat di wajahnya bisa kelihatan.
Jadi, jangan gampang menyimpulkan kalau sebagai ustadz, saya mesti baik. Belum tentu. Biarpun saya selalu mengatakan nuwun sewu (mohon maaf/permisi) setiap hendak menyampaikan sesuatu, bukan berarti saya lebih baik dari semua orang yang hadir di pengajian. Sembahyang saya belum tentu lebih baik daripada sembahyang kalian.