
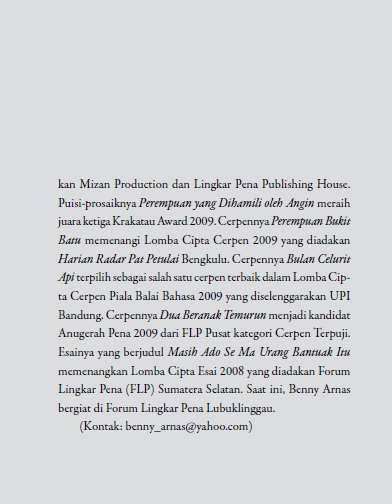
Di antara pendar-pendar cahaya jingga lampu tep lok di atas lemari kayunya, seorang ibu tua menatap foto hitam-putih yang memburam di dinding geribik sebuah bilik. Di foto itu: di antara putri-putri mereka yang masih kecil-kecil, seorang lelaki paruh baya duduk di sampingnya. Suami. Begitulah dulu, laki-laki itu menyandang status terhadapnya. Laki-laki yang—ah, banyak menyisakan kepedihan sekaligus kerinduan di dadanya. Bersamanya, si Ibu Tua ber-anak lima. Perempuan semua. Nah, itulah perkara yang selalu membuat suaminya tersela dalam setiap ingatannya. Suaminya sangat menginginkan keturunan laki-laki.
Ah, itu tak disebabkan suaminya tidak menginginkan keturunan perempuan. Walaupun dipikirkannya jua bahwa mungkin saja, suaminya tidak se-anti itu pada ketentuan yang berlaku terhadap kelamin anak-anaknya, bila ada satu saja dari mereka yang dapat disebut pejantan.
Oh, nyatanya perkaranya lebih dalam dari itu. Keinginan suaminya itu seakan-akan kutukan bagi nasib Ibu Tua yang dahulu tak terlalu mendengarkan petuah lelaki itu. Ibu Tua itu kadung mencintai putri-putrinya ....
“Beruntung sekali kau dapat anak perempuan. Kau tak perlu capai-capai mencuci baju, piring, atau menyiram bunga raya kesukaanmu di pekarangan dan tanaman obat di kebun belakang. Tapi ..., berusahalah berketurunan laki-laki. Satu pun jadi. Yaa kata orang-orang Selatan tu, seumpama memasak sayur lah. Anggap saja, tak ada bujang, tak bergaram. Hambar. Dan, dibuanglah masakan itu ....”
Ibu Tua ingat sekali, kata-kata dari seorang ibu-ibu—yang ia lupa namanya—yang sengaja ditujukan padanya itu. Saat itu, mereka masih berputri tiga. Ketika ia mengadukan perihal itu pada suaminya, seperti sudah diduga, lelaki itu seakan-akan membenarkan ucapan ibu-ibu itu. Yah, seperti biasalah. Seperti sungai yang menganak saja suaminya berceloteh. Mengalir tak berhulu; berulang kali menceritakan ketiada-elokan budi saudara-saudaranya.
“Saudara-saudaraku itu tak tahu bagaimana berterima kasih pada Mak. Mak sakit keras, sampai mati pun tak ada mereka datang menjenguk dan melayat. Mereka sibuk dengan ipar-iparku. Ugh, ipar. Puihh!”
Setengah mengerutu—setengah menyesal—Ibu Tua menge nang bahwa ia pernah menganggap angin lalu saja curahan hati suaminya itu. Ia tahu, suaminya adalah anak bujang satu-satunya. Semua saudaranya perempuan. Tetapi janganlah kiranya terlalu berlebihan menyamaratakan perkara, batinnya kala itu.
“Kakak bertenggang jualah padaku yang sangat senang pada anak-anak gadis kita itu. Janganlah selalu menjaga jarak dengan mereka, Kak. Seperti juragan dan pekerja saja kulihat hubungan kalian.”
Suaminya diam saja.
“Lagi pula, Kakak tahu kan, bagaimana aku di tengah keluarga. Berkebalikan dengan Kakak. Aku satu-satunya perem puan. Bungsu pula. Sering diperlakukan tak selayaknya sebagai manusia, sebagai adik mereka. Layak pembantu aku, Kak. Ah, Kakak sudah tahu itu, kan?” Air mata Ibu Tua mengucur waktu itu.
“Mmm ...” lanjutnya, “Kakak sendiri pernah ngomong, kan, kalau rasa iba pada keadaanku juga menjadi alasan mengapa Kakak menikahiku. Tentu saja, selain karena Kakak memang mencintaiku. Lagi pula, bukan maksud hati tak melahirkan anak laki-laki, Kak. Tetapi ..., tak dititipkan-Nya saja kita, Kak.”
Saat itu, suaminya menatapnya dalam; membelai rambut nya yang disanggul sekenanya, sebelum berbisik lirih. “Semoga keturunan kita selanjutnya laki-laki ya, Dik.”
Bakda itu, di usia yang hampir berkepala empat, sadarlah ia bahwa urusan berketurunan belum usai. Hanya satu doanya. Semoga ia masih diberi kesuburan. Paling tidak, sampai anak laki-laki mengoek dari selangkangannya.
Ternyata Tuhan sangat baik pada Ibu Tua—tapi tak se penuhnya, kurang lebih itulah suara batin terdalamnya waktu itu. Ya, ia memang masih subur, hingga dua anak lagi dilahir kannya. Tapi, semua seakan-akan tak berbias gembira sebagai mana layaknya pasangan menyambut bayi mereka. Ya, dua anak terakhir melengkapkan kenyataan bahwa mereka berputri lima. Dan, tak ada rencana menambah keturunan lagi. Bukan, bukan karena ia sudah capai bertaruh nyawa di hadapan dukun beranak; bukan pula karena suaminya menyerah pada keinginannya, tetapi karena menopause tak sabar lagi bertandang.
“Ahh,” Ibu Tua mendesah. Seakan tersadar dari pengem baraan masa lalunya. “Apakah dengan mendengarkan dan mengiakan pendapat dan keinginanmu bahwa anak laki-laki itu lebih baik, maka Tuhan akan menurunkan takdir yang berbeda pada kelamin yang anak-anak kita usung saat itu, Kak? Tidak ’kan, Kak?” Ibu Tua menatap suaminya di foto itu lekat-lekat. Seolah-olah lelaki itu mendengarkan tuturan dan pembela annya.
Sambil perlahan mendekat ke foto itu, Ibu Tua terus menyemburkan kemarahan yang tak sebenar marah, sesekali mengutarakan pembelaan, atau berujar dengan nada kesal-kesal manja. Tak sadar, jari-jemarinya pun mengelus-elus permukaan wajah suaminya. Ah, khusyuk sekali Ibu Tua melakukannya. Seakan-akan pipi suaminya benar-benar berlekuk, hidungnya benar-benar bangir, atau rambutnya benar-benar klimis oleh minyak kelapa.