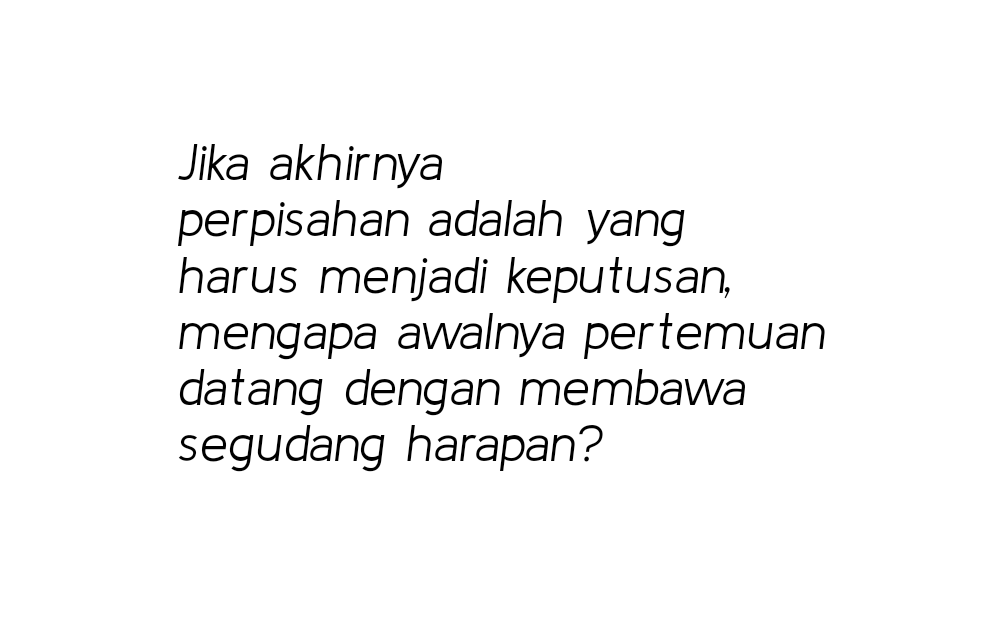

“He, lonte ini mau minta bantuan, ya? Om-om yang biasa sama kamu nggak bisa lagi nemenin?”
“Om-om? Siapa tuh, Des?”
“Om senang, om bayar.”
“Wah, Olivia ternyata mainnya sama om-om? Padahal, dari keliatannya kayak anak polos.”
“Iya, heran, deh, Ka. Cemarin kosan kita aja cewek jalang ini. Cih.”
“Korona kayak gini emang nggak bisa lagi kayaknya, Des. Sayang banget, sih, jadi nggak ada lagi, deh, pemasukan. Hahaha.”
“Haaah!!!” Aku yang terbakar nggak bisa nahan lagi buat nggak teriak. “Kesel bet dah.”
Nggak ada kaleng yang bisa kutendang, akhirnya aku mengentakkan kakiku saja ke trotoar dengan sekuat tenaga. “Mulut isi neraka emang si Rika sama Desi. Always gibah everytime everywhere. Gibah aja terooos. Haaaaaahhh!”
“Om-om, katanya? Seenaknya bet ngomong. Siapa lagi, sih, yang nyebarin gosip nggak bener di kosan. Duh, padahal aku cuma nanya apa ada bantuan korona tadi. Tapi, dua orang itu malah ngajak berantem. Keseeel!” Aku kesal sekali. Kesal. Kesal. Kesaaal. “Haaaaaah!”
Angin berhenti bertiup. Ada hawa-hawa aneh mulai menyelimuti, perasaanku tidak enak. Aku pun ikutan setop, lalu mengedarkan pandangan. Orang sekeliling yang tengah berlalu lalang terpaku ke arahku semuanya. Iya, semuanya.
Aku lupa sedang di jalan umum. Mampus.
Aku menatap satu per satu mereka. Ada yang kumisan sedang menahan tawa; ada juga yang dari ekspresi wajahnya seperti berkata, dasar cewek aneh; dan yang lainnya sekadar pandangan heran. Tidak ada suara yang keluar, tetapi tatapan mereka yang kian melekat kepadaku.
Angin kembali bertiup lembut di telinga dan membuatku tersadar. Aku pun segera menaikkan masker, lalu berjalan seperti tidak terjadi apa-apa.
Astaga maluuu! Bodoh banget kamu, Olivia. Udah kepergok goblok tidak pada tempatnya, malah bengong pula.
Setelah berhasil kabur, aku berhenti di jembatan yang tidak jauh. Di sini sepi dan hanya ada angin yang berembus kencang. Tidak ada lagi orang yang akan terganggu karenaku di sini.
Aku mengambil tempat yang naung, berlindung dari panasnya matahari di bawah bayangan besi jembatan yang melintangi.
Aku menelungkupkan siku di pagar besinya.
“Sial banget aku hari ini.”
Aku menenggelamkan wajahku, mengintip ke bawah di sela pagar besi. Pemandangan Sungai Mahakam yang keruh karena airnya sedang naik memang tidak terlalu bagus. Namun, ini tempat yang sempurna untuk menyendiri dan mengembalikan mood dengan luapin uneg-uneg. Tidak seperti di Jawa, sungai di sini luas sekali.
“Diputusin pacar sampe dikata-katain. Gila, ya, pacaran baik banget, pas putus segitu jahatnya.”
“Terus, tiba-tiba digosipin cewek-cewek kos sama om-om. Malah aku yang diusir karena bikin ribut. Dan, semenjak ada aku, kosan nggak tenang, katanya.”
“Bodo ah, selalu aku yang disalahin. Di mana-mana selalu kayak gitu mulu. Belum juga genap sebulan ngekos di kosan cewek, udah kayak gini aja.”
“Di kosan nyampur cowok, aku yang digodain, aku yang dituduh macam-macam. Di kosan cewek, malah berantem mulu, terus diginiin.”
“‘Cewek itu nggak pernah salah’ kayaknya nggak berlaku buatku.”
“Padahal…, aku sudah bersikap baik ke semua orang.”
Aku menendang-nendang kecil pagar pembatas ini. Angin yang bertiup kencang seakan-akan memberikan jawaban tentang apa yang kukeluhkan. Aku mengangkat kepala dan bertopang dagu.
“Sadar, sih, aku. Dari tatapan mereka yang ngejahatin aku itu keliatannya nggak beda."
“Tatapannya sama.”
“Penuh kedengkian.”
“Bukan sekadar iri karena mereka nggak dapat keberuntungan. Tapi, dengki karena nggak senang ngeliat aku senang.”
“Masalah banget gitu, ya. Ngeliat orang senang dikit, langsung kebakar hatinya. Itu hati apa gas elpiji? Dah bau busuk, gampang banget kebakar pula.”
“Nggak ada, ya, yang nggak iri gitu ke aku. Aku nih apa juga yang mau diiriin. Nggak habis pikir, deh. Pinter nggak, goblok iya. Tinggi nggak, pendek iya.”
Aku mendengkus. Lelah rasanya. Mataku rasanya berair entah kemasukan debu, langsung kusapu dengan telunjuk.
“Nggak cuma hari ini kayaknya sial, hari yang sudah-sudah pun aku sial juga.” Aku tidak ingin mengingatnya.
“Apa bisa lebih sial lagi gitu. Kayak….” Aku menengadah ke atas. “Jembatan ini ambruk kayak delapan tahun yang lalu gitu. Pas banget aku lagi berdiri di sini, terus aku keseret arusnya yang deras sampai hilang dari peradaban.”
Aku menghela napas panjang. “Nggak mungkin kali, ya. Nggak mungkin dunia sejahat itu.”
“Kalau ambruk beneran, nggak masalah buatku buat renang ke tepi, sih. Soalnya, ini nggak terlalu di tengah.” Aku mengatakannya sambil melihat-lihat rangka baja jembatan yang tampak masih kokoh. Cahaya matahari tengah hari menembus baja yang saling menyilang menyilaukan mataku. Jarang-jarang aku memperhatikan jembatan ini, karena lebih seringnya ke pemandangan. Rupanya bagus juga.
Bersandar di jembatan memperhatikan bayangan matahari menyilang di jalan, aku mendengkus lagi entah yang keberapa kali. “Aku harus ke mana? Aku kena kutukan apa gimana, nggak adakah tempat yang nyaman di sini? Aku kan cuma ingin diterima. Mau pulang pun nggak bisa, korona gini.”
“Ah, aku jadi pengin pulang saja…. Kangen Mama, pengin meluk.”