Brian membiarkan dirinya larut dalam pesona makhluk ciptaan Tuhan bernama wanita. Apa pun gerakan yang dilakukan oleh sosok itu segalanya terlukis mengagumkan. Wanita di depannya berdiri menghadap jendela geser melakukan percakapan via telepon. Seulas senyum kian menambah paras manis di wajah itu. Sangat kontras dengan ukuran tubuh ramping nan mungil tersebut. Brian tersenyum, memutar ingatan untuk menggapai tangan si wanita agar tidak meninggalkannya. Tetap berada di sisinya.
***
"Kenapa kau mencarinya? Bukankah kemarin kalian bertemu?"
"Benar. Tapi sekarang aku menyesal karena pergi begitu saja. Aku tidak bisa menghubungi Grace atau Rehan."
"Mereka pasti sedang sibuk. Dan jika kau bertanya di mana Indira? Tentu saja dia berangkat ke bandara. Mungkin saja sudah sampai dan bersama istriku sekarang. Kau tidak tahu?"
Percakapan itu berlangsung sepuluh menit lalu yang dilakukannya dengan Profesor Rasyid saat berada di kamar suite hotel. Brian merasa bodoh atas pertemuannya kemarin. Dia meninggalkan Indira setelah mengucapkan permohonan maaf. Tanpa menunggu respon dari gadis itu. Tanpa memberi tahu maksud kedatangan dirinya yang sebenarnya. Dia tidak kuasa menatap mata bening Dira saat mereka bertemu.
Bukan hal mudah bagi Brian menunjukkan dirinya di depan Dira. Seperti pengintaiannya dulu, dia hanya mengamati gadis itu dari jauh saat keluar dari rumah sakit. Dia memutuskan sementara waktu kembali ke Kanada. Dia selalu takut jika menatap Dira dalam jarak yang cukup dekat. Hal tersebut akan membangkitkan rasa sesal atas segala penderitaan Dira. Bahkan membayangkan kembali melihat lelehan air mata saat gadis itu koma, seolah hatinya pun larut dalam kesedihan. Dia harus mengakui apa yang dikatakan Takeshi saat itu.
Origami itu sudah kuberikan pada si gadis dari Indonesia saat berlibur ke Bali. Aku bahkan menyuruhnya memanggilku dengan Nii-chan. Panggilan yang manis, bukan? Semanis wajahnya. Lebih baik tidak kuceritakan. Aku takut kalau kau akan mencarinya nanti.
Kecurigaannya itu timbul sejak melihat Dira masuk ke ruangannya menatap foto Takhesi dengan mengucapkan ‘Nii-chan’ seolah panggilan tersebut sudah sangat akrab untuk diucapkan. Dia begitu senang mengetahui Dira-lah si gadis Indonesia yang dimaksud oleh Takhesi. Terlebih lagi ketika mendengar secara langsung pengakuan dari gadis itu.
Louis memberi kabar bahwa Dira akan berangkat ke Indonesia usai acara wisuda. Maka sebelum bertemu, dia memikirkan cara menyampaikan tujuannya lewat dua tiket penerbangan, yakni Indonesia dan Kanada yang dimasukkannya bersama origami serta bingkai sketsa dalam paper bag cokelat untuk diberikan pada Indira. Dia menunggu jawaban dari gadis itu.
Kenapa Indira belum memberi balasan? Brian bertanya pada dirinya sendiri. Dia sulit berkonsentrasi dengan apa pun. Merasakan kebuntuan yang menyesakkan. Hanya berputar di suite hotel sejak menyelesaikan pekerjaannya. Dia kembali menatap layar laptop yang masih menyala. Memandangi jam dinding terus mengitari angka-angka setiap sisi sudutnya. Dia bahkan telah meredam isi kepalanya dengan mandi dan menunaikan shalat untuk menahan diri agar tidak menuju ke apartemen Dira. Namun tidak berhasil mengusir kecamuk hatinya.
Brian berinisiatif untuk menghubungi Grace juga Rehan. Tidak tersambung. Kemudian pilihannya jatuh pada Profesor Rasyid. Setelah mendapat kabar dari pria itu, bagian resepsionis menelepon, mengatakan bahwa dirinya mendapatkan paket berasal dari alamat apartemen Dira. Tentu saja dia bergegas mengambil benda itu. Sejenak matanya tertumbuk pada dua buah tiket penerbangan. Masih utuh. Dira tidak memilih keduanya. Ternyata gadis itu lebih memilih kembali ke Indonesia tanpa menggunakan tiket yang diberikannya.
Brian berlari menuju pintu masuk bandara. Dia tidak bisa kehilangan kesempatan lagi. Mungkin ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan atau dia akan dipenuhi penyesalan seumur hidupnya. Tatapan Brian menunjuk ke segala arah. Dia terus mencari sosok Indira. Naik dan turun kembali dari eskalator di terminal bandara. Menghentikan setiap wanita seperti sosok yang sedang dicarinya. Dia pun mendengar bagian informasi-komunikasi menggemakan panggilan jadwal keberangkatan di area itu. Hal tersebut menambah kegundahan Brian. Dalam cekaman rasa putus asa, dia mengambil langkah. Memupuk keberanian menuju asal gema suara itu.
Brian memulai aksinya. Mengeluarkan suaranya di depan mikrofon.
"Indira, wherever you stand, please stop where you are right now!"
"Kumohon hentikan langkahmu. Entah hal ini benar dilakukan atau tidak, aku merasa konyol membohongi diriku sendiri. Berbohong tidak masalah tidak melihatmu. Berbohong bahwa aku akan baik-baik saja tidak mendapatkan kabar dan mendengar suaramu lagi. Sungguh ironis sekali, bukan? Saat ini aku tidak tahu malu mengharapkan jawaban yang ingin kudengar darimu."
Brian memberi jeda pada ucapannya. Dia menghela napas. Setetes air mata jatuh perlahan menyentuh punggung tangannya. Lalu berkata kembali, "Maafkan aku atas semua kesakitan dan penderitaan yang kau alami karenaku. Maafkan atas senyum yang pernah kurenggut darimu. Maafkan bahwa dari semua hal yang telah kulakukan, ternyata tidak bisa memupus perasaanku padamu. Tidak bisa membuatku menjauh. Namun jika kau menolaknya, kumohon berikan kesempatan padaku untuk mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan kebahagiaanmu. Kumohon. Beri aku kesempatan. Setelah itu, aku tidak akan muncul atau pun mengganggu hidupmu lagi."
Brian menyelesaikan misinya. Dia meminta maaf pada staf yang berada di sana, karena telah memaksa memperbolehkannya menggunakan ruangan itu sehingga mengganggu pekerjaan mereka. Dia melangkah ke pintu, keluar dengan gontai dan lemas. Tidak bersemangat. Tetiba tapak kakinya berhenti bekerja. Berhenti bergerak. Hanya karena melihat sosok gadis berkerudung biru navy berdiri tepat selangkah di depan matanya.
"Kenapa kau mengganggu pekerjaan orang? Kau memang egois, ya! Itukah caramu agar semua orang bisa mendengar keinginanmu?"
Komentar Indira barusan belum sepenuhnya membuat Brian sadar akan keberadaan gadis itu di depannya. Dia masih diam memandangi Dira. Takut jika dirinya sedang berhalusinasi.
"Aku yakin kau pasti belum membaca pesanku," ujar Dira mengeluarkan ponselnya. "Kau bisa lihat ponselmu. Tunggu. Jangan bilang, kau juga tidak membawanya?"
"Apa?" Brian mencari di saku jas dan celana hitam panjangnya. Ternyata dia memang tidak membawanya. Tertinggal di suite hotel.
"Aku ke bandara ini menjemput Madame Eliya. Bukankah Profesor sudah memberitahumu?" Dira menghela, lalu berkata, "Aku merasa tidak enak sekarang, karena membiarkan Madame pulang sendiri. Untuk itu, kau harus bertanggung jawab menenangkan hati Beliau."
***
Senyum Brian tidak lepas dari bibirnya. Dia mengamati layar ponsel. Sederet tulisan membuatnya merasakan kehangatan lewat gemuruh jantungnya memberikan ritme cepat.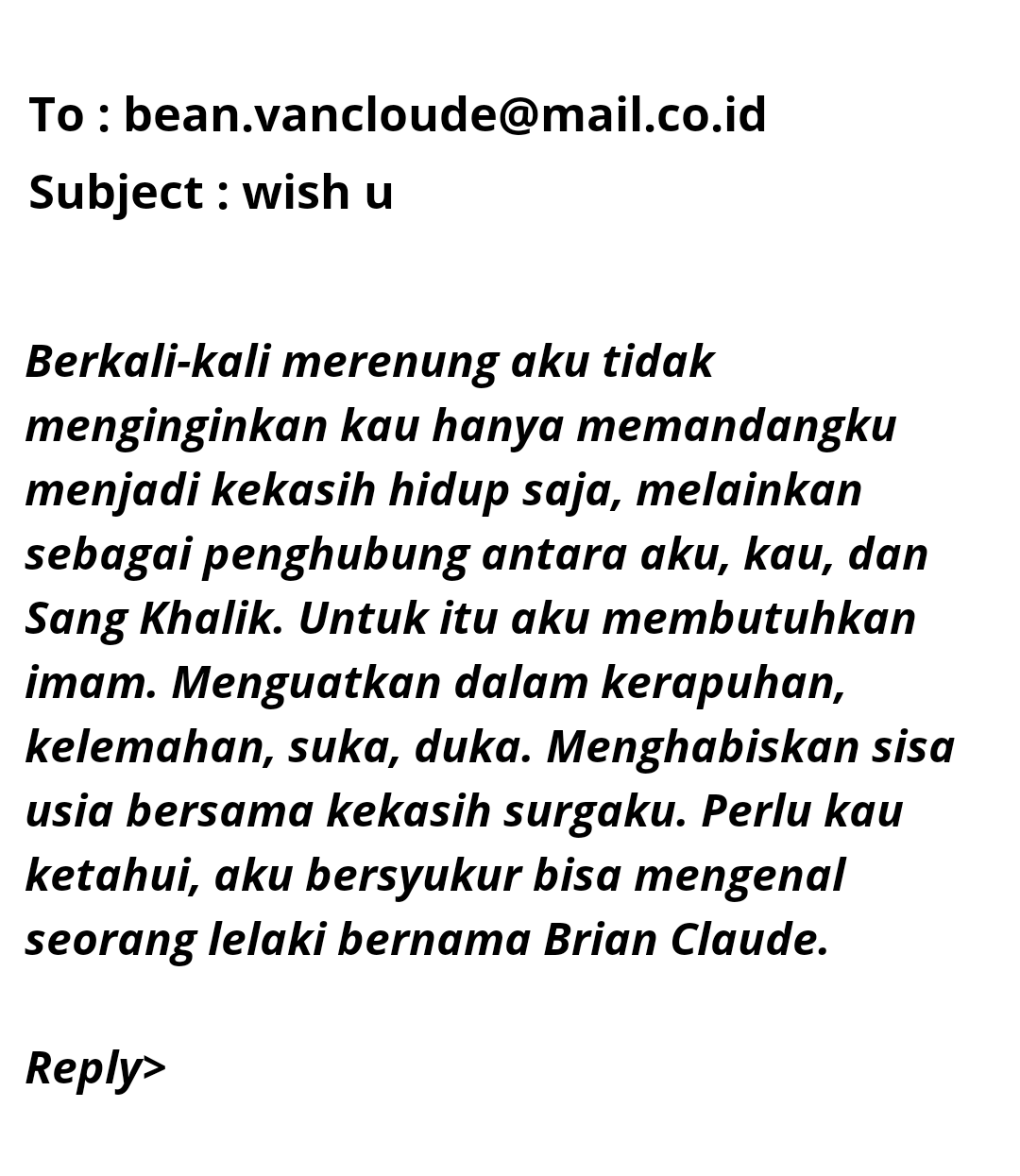
Tepat saat Dira mengakhiri percakapan, sejurus kemudian matanya menangkap sosok Brian bersandar di pintu. Sudah lamakah lelaki itu ada di sana? Dan apa yang membuatnya tersenyum cerah seperti itu? Namun lagi-lagi gejolak debar jantungnya muncul. Seperti saat dirinya membaca isi di surat itu.
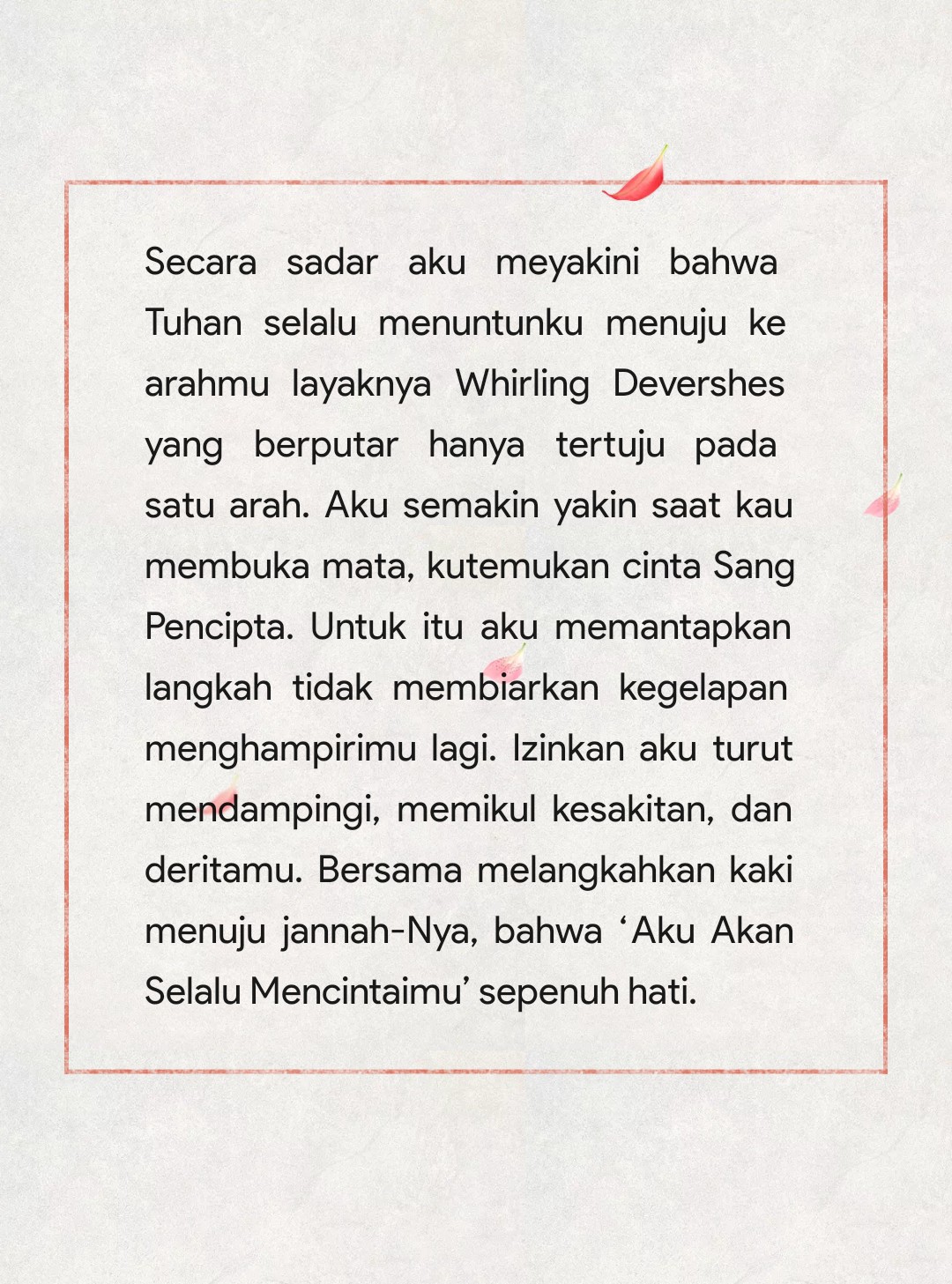
Usai Brian meninggalkannya, hatinya turut diliputi kebingungan dan gelisah. Dia tertegun ketika mengeluarkan benda dalam paper bag tersebut, juga terdapat amplop cokelat. Berisi dua lembar tiket penerbangan Indonesia dan Kanada. Sebuah surat terlampir di sana. Terang saja jantungnya menderu. Bahkan Grace yang saat itu memasuki kamar terkejut melihat tangannya ke dada, berusaha menenangkan debaran yang menelusup.
"Apa yang terjadi? Apa penyakitmu kambuh lagi? Perlukah kita memanggil Dokter?"
"Tidak. Aku baik-baik saja. Aku hanya perlu menenangkan diri."
"Menurutku tidak demikian. Kau masih saja ingin berbo--"
Grace mengamati benda-benda di meja. Sekilas terbaca olehnya tulisan di kertas yang terbuka itu. "Tunggu, apa ini? Kau bertemu Brian? Dan dia memberimu kejutan seperti ini?"
"Apa yang harus kulakukan Grace?"
"Bukan padaku. Tapi tanyakan pada hatimu, Dira. Karena hanya dirimu yang tahu di mana saat ini posisimu berada. Sama seperti yang pernah Ibu katakan, 'hatimu akan mengarahkan logikamu. Kemudian dari logikamu menentukan koordinat destinasimu dan cernalah perkaramu dengan ketenangan melalui doa yang dipanjatkan'. Kau ingat itu, kan?"
Benar. Kalimat itu digaungkan oleh ibunya. Mengingatkan dirinya di saat kebuntuan dan dalam kebimbangan. Dia pun menerapkan hal itu dan mengirimkan kembali amplop cokelat pemberian Brian ke hotel.
Indira, wherever you stand, please stop where you are right now!
Alangkah terkejutnya ketika suara lelaki itu menggemakan kalimat tersebut di seluruh penjuru terminal bandara. Madame Eliya yang bersisian dengannya bertanya heran melihatnya berhenti.
"Ada apa? Mungkinkah karena suara yang muncul barusan? Memangnya siapa orang iseng yang membuat kehebohan di tempat ini?"
Madame Eliya mulai memfokuskan pendengaran. Meski wanita itu tidak tahu isi ucapan yang dilontarkan berbahasa Indonesia, namun dia mulai mengerti dan bahkan tertawa saat mengenali suara yang akrab di gendang telinganya.
"Kau juga merasa demikian, Dira? Oh ya, ampun... Aku tidak menyangka sifat kekanakannya bisa muncul seperti itu karena sedang jatuh cinta!" Madame Eliya menggelengkan kepala dan berkata, "Kenapa kau memasang ekspresi panik begitu? Seharusnya itu aku, Sayang. Daripada dia membuat kekacauan yang lebih serius, temui dia sekarang juga. Sepertinya aku memang diharuskan pulang tanpa ditemani siapa pun."
Wanita itu tersenyum dan pergi meninggalkannya sembari melambaikan tangan saat menyeret koper. Padahal Beliau meminta mengantarkan ke rumah sakit menjenguk Grace yang telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Melihat Brian berdiri di depan microfon, mengeluarkan semua kalimat yang tertuju padanya, membuat dia terpukau. Membuncahkan hatinya oleh ketulusan dari lelaki itu. Menenangkan.
Pukul delapan tepat menjadi momen paling sakral baginya melaksanakan prosesi aqad. Air matanya menderas di kala Grace memberikan kado teristimewa. Gaun pengantin.