Dia memang selalu begitu, dingin.
Tapi begitulah dia, dan aku menyukainya tanpa banyak protes,
seperti aku menyukai mint ice cream yang membekukan lidahku.
Hampir sepuluh menit aku dan Leon duduk di depan Bu Patricia dengan tampang
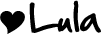
reporter yang siap siaga. Sayangnya, Bu Patricia lebih memperhatikan kuku-kukunya yang bercat merah menyala. Kalau tidak ingat dia atasanku, aku pasti sudah menerkamnya, mencabuti kuku-kukunya sambil berteriak-teriak mengingatkan bahwa dia yang memanggilku ke sini, mengingatkan bahwa di luar sana semua reporter sedang kalang kabut melaksanakan segala ide anehnya, mengingatkan juga bahwa, halooo … ini sudah detik-detik makan siang!
Tapi, nyatanya aku tak berani bersuara, cuma duduk kaku dan saking sudah lamanya, sebentar lagi pasti jadi arca. Leon, fotografer ganteng yang duduk di kursi sampingku, terang-terangan melihat jamnya. “Saya tidak bisa lama. Ada deadline yang harus saya kerjakan. Lagi pula, ini sudah jam makan siang,” katanya dengan suaranya yang berat. Nadanya kalem dan tenang.
Aku lebih suka menunggu sejuta tahun lagi daripada mengatakan hal lancang seperti yang Leon katakan barusan. Bu Patricia menengadahkan wajahnya yang mengerikan. Ia seperti baru tersadar ada dua ekor anak buahnya yang dari tadi duduk di hadapannya. Tatapannya beralih dari kuku-kukunya dan jatuh kepada Leon. Semoga cowok cakep ini selamat. Bu Patricia menghela napas, “baiklah, Leon. Kamu memang nggak pernah sabar.”
Ha? Hanya itu komentar Nenek Sihir jahat ini? Kalau yang barusan mengganggu keasyikannya adalah aku, sekarang pasti sudah ada ambulans di depan kantor untuk menjemputku. Bu Patricia akan menggunakan kuku-kukunya untuk mencakarku sampai puas. Ekor matanya melirik lagi pada kuku-kuku merahnya. Uh …, kuku-kuku merah itu, tentu saja sempurna. Dia, kan, nggak pernah melakukan apa pun dengan tangannya sendiri. Dia tidak pernah mengorek-ngorek bawah batu, mencari umang-umang untuk mendapatkan detail deskripsi keong sialan itu. Jangankan melakukan tugas hina itu, mengetik artikel pun ia tidak pernah. Buat apa punya begitu banyak reporter dan redaktur? Prinsip hidupnya: delegasikan semua tugas, seberapa pun mustahilnya tugas itu.
Kemudian, ia tersenyum menatapku dan Leon bergantian. Senyum palsu, tentu saja. Aslinya, Bu Patricia tidak punya lengkungan mulut ke atas. Selalu ke bawah. Namun, karena ini Leon, fotografer berbakat kesayangannya, tentu saja ia rela melengkungkan mulutnya ke atas. Aku yakin habis ini dia pasti kram bibir.
“Begini … saya memutuskan kalian berdua yang akan betugas untuk liputan rubrik ‘Wherever You Want’.” Ada jeda. Bu Patricia pasti menunggu reaksi kami. Tentu saja aku girang, senyumku melebar. Aku memang menginginkan tugas ini. Aku tidak bisa pura-pura terkejut. Memangnya siapa lagi yang akan diutus untuk proyek sepenting ini kalau bukan reporter yang paling berbakat?
Pada ulang tahun yang ke-30 ini, Travel Lovers Magz juga mengadakan polling pembaca, dan aku adalah reporter favorit mereka. Selain itu, aku adalah reporter teladan tahun ini. Mungkin ini adalah tahun keberuntunganku. Keberuntunganku yang satu lagi, datang hari ini. Aku akan pergi liputan bersama Leon! Para reporter perempuan jelas bersedia saling membunuh untuk mendapatkan tugas ini.
“Saya akan mengumumkannya pada rapat redaksi besok, dan saya akan menyuruh Damia untuk mengurus perjalanan kalian. Sebaiknya, kalian bereskan semua deadline kalian dan berangkat lusa,” lanjut Bu Patricia dengan nada yang sama dengan, Bereskan semua sampah-sampah kacang di lantai itu! Sepele bin gampang.
“Ada pertanyaan?”
“Berangkat liputan ke mana?” tanya Leon.
“Belum ditentukan, tunggu hasil polling besok, pukul 12 malam,” jawab Bu Patricia tegas.
“Apakah … hanya kami berdua yang bertugas?” Aku bertanya sambil melirik Leon, berusaha menangkap ekspresinya. Namun, tak ada ekspresi apa pun, manusia ini pasti nggak punya otot wajah. Dengar berita yang begini heboh pun nggak ada reaksinya.
“Tolol! Tentu saja cuma berdua. Reporter favorit dan fotografer favorit.” Bu Patricia kemudian terkekeh seperti nenek sihir. “Pembaca pasti menyukai ide brilian ini! Lagi pula, kamu pikir ini perusahaan mbahmu? Perusahaan nggak akan ngangkut semua anggota rombongan topeng monyet di kantor ini untuk liputan yang makan biaya begini banyak!”
Aku mengangguk patuh. Wajahku takut, tapi hatiku meletup girang. Persetan dengan apa yang dia maksud dengan anggota rombongan topeng monyet itu, yang jelas pertanyaanku sudah terjawab. Aku hanya akan pergi berdua dengan Si Cakep Leon. Berdua! Mwahaha! Indahnya hidupku.
“Baiklah kalau begitu, Bu. Saya janji, saya dan Leon akan mengusahakan yang terbaik.” Aku tidak bisa lagi menutupi rasa girangku. Aku menoleh kepada Leon. Setidaknya, ia tinggal mengangguk, atau menjawab ‘Iya’. Namun, cowok ini malah menengok kepadaku dengan wajahnya yang salah ekspresi, harusnya dia bisa membedakan ekspresi kesal dan setuju.
“Saya tidak ingin menjanjikan apa-apa,” kata Leon tegas kepada Bu Patricia.
“Baiklah, saya juga tidak butuh janji. Kalian lanjutkan masalah janji-janjian atau apa pun itu di luar,” kata Bu Patricia tidak peduli. Leon beranjak dari kursinya, tanpa bicara, juga tanpa menoleh calon partner sehidup-sematinya beberapa minggu ke depan.
Dia memang selalu begitu, dingin. Namun, begitulah dia, dan aku menyukainya tanpa banyak protes, seperti aku menyukai mint ice cream yang membekukan lidahku. Dia mirip seperti itu, paling dingin dari yang terdingin.
Aku mengekorinya.
Selintas aku mendengar Bu Patricia mendesis, “Hus … hus … hus ….”
Juno, editor mode yang harusnya kerja di ruangannya sendiri malah ngeronda di mejaku. Dari jauh saja aku tahu itu dia, memangnya siapa lagi di kantor ini yang memakai syal bulu-bulu ke kantor selain orang yang punya stok malu tak terbatas? Kali ini si manusia yang punya stok malu tak berbatas itu mengenakan syal bulu-bulu berwarna hijau, sewarna dengan rambutnya. Ah, ya, rambutnya pun baru. Kalau tidak salah kemarin warnanya ungu atau pink. Aku baru tahu ada orang yang rela mengecat rambutnya demi terlihat matching dengan syal norak itu.
Dari wajahnya yang berseri-seri dan senyumnya yang janggal, aku tahu apa yang dia inginkan.
“Minggir. Kursi gue!” kataku.
“Duh … galak amat. Pantesan nggak ada yang mau sama lu, Leon. Muka boleh ganteng, tapi mulut kayak petasan.”
Dengan malas Juno berdiri dari kursiku. Sementara aku duduk, ia menyandarkan pinggulnya ke pinggiran mejaku. Dia pikir lagi syuting film Sekretaris Penggoda? Dia menggoyang-goyangkan syalnya, pasti minta komentar penampilannya yang baru ini. Tidak akan! Aku bertekad tidak akan mengomentari penampilannya!
“Syal gue baru, lho. Warnanya dapet banget, ya, makanya gue juga ngecat rambut gue pakai warna ini.”
Aku meliriknya tajam dengan isyarat “DIAM KAU!”
Sepertinya, Juno tidak paham bahasa isyarat. Dia malah meraih lengan kemejaku. “Kemeja baru, ya? Armani? Kenapa ambil warna hitam, sih? Kayaknya model ini dia ngeluarin yang warna hijau, deh. Kenapa nggak ambil yang warna hijau? Kan, bisa kembaran sama gue!” katanya ceriwis.
“Gue nggak mau kelihatan kayak ulat.”
“Duh, dasar deh mulut petasan. Lu pikir gue kayak ulat?”