
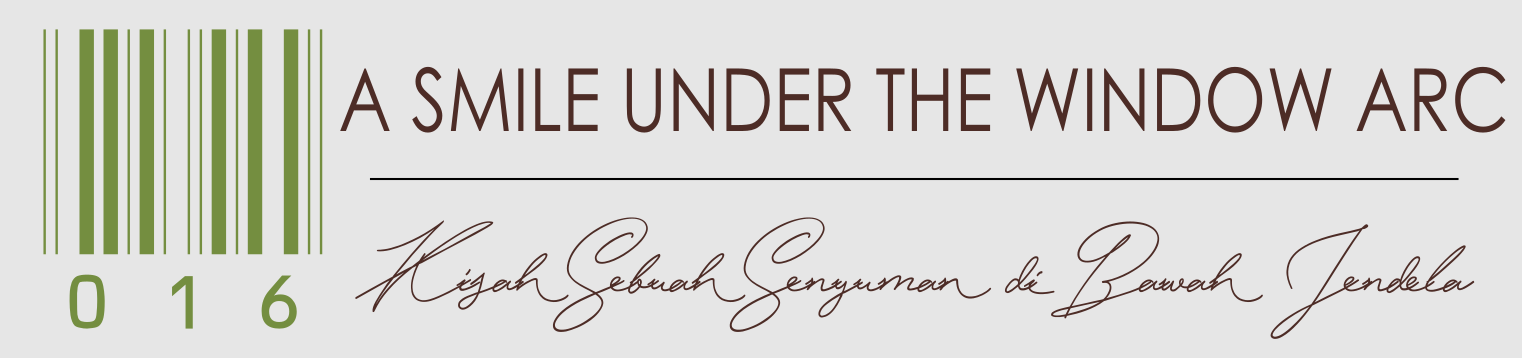
“Ada apa lagi? Kalian kayaknya gak akrab banget.” Rawi membawa Jati di ruangannya, sedangkan Haw dan Bana beristirahat di sebelah—gudang pribadi milik sang CEO yang cukup layak digunakan sebagai tempat istirahat.
Di sisi lain. Bana menyodorkan segelas coklat hangat, yang barusan dibuat dengan meminjam dispenser di gedung ini. Dia melingkarkan kemeja miliknya—kebetulan hari ini dia mengenakan pakaian tersebut rangkap dengan kaos—pada Haw. Tak bisa berhenti khawatir, meski gadis itu telah berganti baju kering. “Baikan?”
Haw menunduk, duduk sambil memeluk lutut yang tertekuk. Perlahan dia mendongak, menatap pemuda itu.
Bana memasang senyum tipis. “Gak apa-apa. Kalo lu mau cerita sesuatu, gue bisa dengerin. Kalo belum siap, gak apa.” Dia lantas teringat sesuatu. “Juga … kalo lu pengen sendirian, gue bisa pergi, kok.”
Sudut bibir Haw terangkat kecil. Sorot matanya tampak sayu. Dia menggeleng sedikit. “Mana mungkin gue bersikap kayak gitu? Gue sangat bersyukur lu mau nemenin di sini.”
Sementara di ruangan sang CEO, pendingin udara kencangnya seolah tak bekerja. Jati muak berada di sini, terlebih Rawi memaksanya. Dia mendengus lirih. “Bocah itu kebanyakan tingkah aja.”
“Mirip seseorang, bukan?”
Jati spontan menatapnya seraya mengerutkan alis. “Apa lu bilang?”
Tawa kecil terdengar dari mulut Rawi, selagi dia sibuk mencari-cari sesuatu di antara salah satu lemari besar di ruangan tersebut. “Nah, ketemu. Untung saya beli perban buat jaga-jaga.”
“Kenapa?”
“Karena saya tahu, sesuatu seperti ini pasti bakal terjadi.” Rawi menghampiri Jati, dan seketika mendapat tatapan tajam tak mengenakkan dari pria muda itu. Namun, dia tak peduli. “Lepas pakaianmu.”
“Nga—ngapain?” Jati spontan menjauh saat tangan Rawi meraih kerah kemejanya. “Gue bisa sendiri!”
“Jangan ngarang. Masang perban di tubuh sendiri itu kayak menggaruk punggung, bakal sulit dilakukan tanpa bantuan orang lain.” Rawi tersenyum aneh, kian mendekat pada Jati. “Lihat, kamu baru aja ganti baju, tapi kemejanya udah agak basah lagi.”
Jati spontan menepis Rawi yang hendak melepas kancing kemejanya. Sejurus kemudian, dia agak gelagapan saat tiba-tiba orang itu berhasil memegang erat tangannya, dan bahkan tak bergeming walau Jati menatap dengan kian menusuk. “Gak mau, ya! Gak mau, ya!”
“Masih cerewet, ya,” Rawi mendekatkan wajah ke pria muda itu, “kamu ini.” Lantas melayangkan jemari yang menggenggam erat.
Selang sekian menit kemudian, Rawi tampak senang berceloteh tiada henti mengenai keuntungan perusahaannya yang terus meningkat. Dia tersenyum sumringah sambil dengan lihai memutar-mutar perban di sekitar punggung, dada, dan pundak Jati.
Sementara si pria muda murung sejak tadi. “Kenapa harus elu sih?” Dia memegang dahi yang agak memar. “Sakit tahu.”
“Saya cuma mukul pelan, bercanda doang.” Dia mengikat perban terakhir. “Beres!” Lantas menampar kencang punggung punggung Jati.
“Sakit!” Jati spontan memekik, nyaris mengamuk. “Luka gue bentar lagi sembuh, jangan dibikin parah lagi!”
Rawi beranjak dari kursi panjang tempat keduanya semula duduk, memandang Jati sedikit mengernyit seraya meletakkan tangan di pinggang. “Kamu gak boleh balik ke rumah sakit lagi, tahu.”