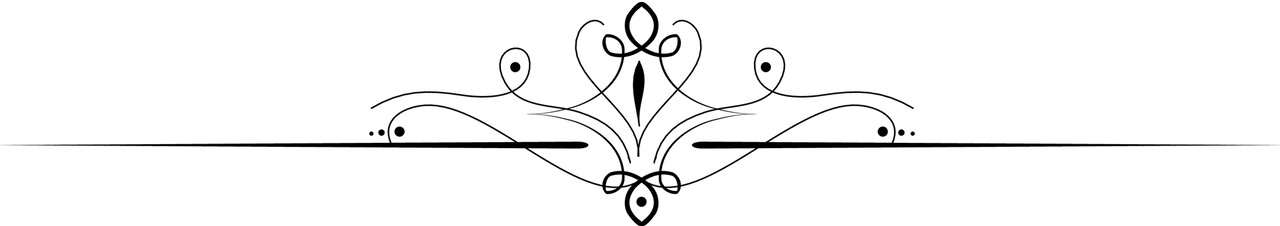
Antari terbaring sembari menatap langit-langit kamarnya, benang merah terajut di benaknya. Ingatan baik dan buruk tercampur jadi satu. Hatinya mati rasa, ia sudah tidak bisa lagi bersukaria di kenangan manis dan berduka di kenangan pahit. Sang bintang jatuh menembus ke inti bumi, membuat gejolak lara kembali bersemi.
Dahulu, kerikil kecil mencoba mengetuk atmosfernya, tapi lama-kelamaan orang itu melempar lebih banyak kerikil. Perlahan tapi pasti, perisai yang melindungi dirinya mulai runtuh. Membuat lubang di lapisan ozon, membakar asa hingga pupus tak bersuara. Tidak ada lagi bunga yang bernyanyi di bawah pepohonan rindang. Sepanjang tahun membeku, tanpa menyangka cahaya matahari menyapa. Layaknya kepingan es di danau musim panas, ia mencair dengan senyuman di wajahnya.
Langit Utara merayakan sehatnya bumi. Pantai Selatan bermain dengan ombaknya. Para burung menyebarkan berita bahwa bumi kembali hijau. Bumi yang mengagumi sinar matahari, bumi yang mencintai hangat matahari, bumi yang akhirnya terbakar karena mengejar afeksi matahari.
Saat itu, senyuman Raditya melelehkannya. Senyum kecut dan mata yang tidak fokus menjadi lukisan terbaik di memorinya. Kemeja dan celana bahan yang selalu berwarna pastel, tegas sekaligus menenangkan. Rangkulan dan kecupan di dahi membuat jantungnya berdegup, persis seperti kelinci yang melompat-lompat kegirangan di taman. Lelucon yang tidak lucu dan gurauan yang menyebalkan merupakan topik kesukaannya, Antari akan menyengir seperti keledai bodoh. Satu-satunya yang Antari setujui tanpa pikir panjang adalah argumentasi kecil mereka di tengah malam. Saat itu, merupakan titik terdekatnya dengan Raditya.
“Tolong lupain aku, Tar,” katanya di panggilan malam itu.
Antari meracau, mempertanyakan apa yang harus ia lakukan untuk melupakan seorang mentari? Bahkan saat purnama, Antari masih bisa melihat refleksi wajahnya. Bintang-bintang di langit malam menjadi saksi bisu ia menangis di kamar atap selama beberapa hari terakhir. Antari berbisik, berharap nebula menyelimuti Raditya dengan pesan renjana di relung hatinya.
“Kalau kamu terlalu dekat dengan matahari, kamu bisa terbakar,” kalimat Semesta menggema.
Bukankah ia terlalu ikut campur? Apa yang ia ketahui mengenai hubungannya dan Raditya?
Permainan takdir ini tidak adil. Seolah-olah hanya Antari yang mengejar, tanpa adanya timbal balik. Bukankah ini yang terjadi ketika kita mencoba terbang dan memeluk kapas di langit siang? Tubuhmu akan terhempas ke lautan, tenggelam, dan terlupakan. Saat ini sedang kemarau, tapi samudra sangat dingin. Mungkin ia terjatuh di antartika.
Penglihatannya semakin buram. Ada cahaya putih yang mengejarnya, objek asing yang terhubung ke permukaan. Tangan Antari berusaha meraihnya, namun tubuhnya sudah menyentuh dasar. Antari tersenyum, cahaya itu membalas pelukannya. Rasanya dingin, membuat sekujur tubuhnya kaku. Semuanya ilusi. Objek itu membekukannya hingga tak berdaya.
Belum, belum saatnya ia menuju alam baka. Antari terbangun diantara para bintang, diselimuti nebula. Di depannya seorang pria berjalan menjauh seakan-akan meminta Antari untuk mengikutinya. Bulan, pria itu menuntunnya menuju bulan, menjauhi matahari. Antari bertanya untuk apa ia menghalanginya? Pria itu tersenyum sembari mengatakan, “Jika kamu terlalu dekat dengan matahari, kamu akan terbakar.”
Antari menggeleng. “Apa yang harus aku lakukan? Bahkan purnama merefleksikan sinar matahari.”
Pria itu mendekati Antari, lalu memeluknya seperti kaca yang rapuh. “Lantas, apa yang kamu takutkan? Semesta berada di pihakmu.”

Ketukan yang sama di tiap pagi, siang, dan malam. Ia harus makan, katanya. Namun kali ini, bukan Salma atau Adam yang mengantarkan nampan berisi nasi dan lauk, melainkan Semesta.
“Kamu pucat,” komentarnya.
Antari tidak menjawab
“Kedatangan saya ke sini ingin meberitahu kamu kabar baik dan buruk. Kabar baiknya adalah nama kamu membaik, sedangkan Ghea menerima sanksi sosialnya.”