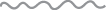Ada ruang-ruang kelam dalam hati manusia,
salah satunya ditempati rasa bersalah.
Satu setengah tahun lalu.
Isvara berlari terseok-seok, sesekali menyeka titik-titik keringat di wajah bulat telurnya. Tengkuknya yang tertutupi rambut bergelombang sebahu bahkan sudah dibanjiri peluh. Isvara mendongak sambil memicingkan mata, menatap matahari yang menyorot ganas. Padahal, waktu baru menunjukkan pukul setengah sebelas, tetapi panasnya sudah terasa membakar kulit. Isvara bergerak refleks, saling menumpangkan kedua tangan, bermaksud melindungi kulitnya. Dalam kepalanya, muncul iklan-iklan kecantikan: cantik itu putih dan langsing. Dia ingin memenuhi standar cantik itu. Jangan sampai kulitnya gosong.
Calya dan Afreen yang awalnya berlari terpaut beberapa meter di depan Isvara, tampak keluar dari lapangan sambil terbatuk-batuk, mungkin kehabisan napas. Sedang Isvara masih menyisakan satu putaran lagi. Kini, hanya tinggal dia dan Bayu, itu pun karena Bayu mendapat hadiah tambahan dua keliling setelah beberapa kali membolos. Seusai peregangan, Bu Rina, guru olahraga, selalu menyuruh siswa-siswinya mengelilingi lapangan tiga kali sebelum masuk ke menu utama pelajarannya.
Pandangan Isvara tertuju kepada Bu Rina yang bergerak lincah memainkan bola basket di tengah lapangan. Isvara merutuk dalam hati, seandainya saja tak ada Bu Rina serta jam olahraga terkutuknya, sekolah pasti akan menjadi tempat yang lebih menyenangkan. Isvara yakin, sebagian besar siswa sependapat dengannya. Isvara teringat kata-kata Afreen, sahabat satu gengnya. “Buat apa, sih, ada pelajaran olahraga segala? Nanti kita kerja juga pake otak. Cuma orang bego yang kerja ngandelin otot! Lagian, kita udah kelas dua belas gini, mendingan belajar daripada panas-panasan.”
Isvara menatap Afreen dan Calya dengan sorot meminta tolong. Kedua gadis itu balik menatapnya sambil meringis. Tiba-tiba, sebuah suara mengalihkan perhatiannya. Suara itu bahkan menyedot atensi seluruh siswa di lapangan.
“Kenapa keluar?” teriak Bu Rina galak. “Kamu belum selesai, ‘kan? Jangan kira saya tidak memperhatikan!” Sebelah tangan Bu Rina bertolak pinggang, matanya yang menyipit tajam menatap Bayu.
“Saya capek, Bu! Emang Ibu mau tanggung jawab kalau saya mati di sini?” protes Bayu tak kalah keras.
Wajah Bu Rina yang tirus mengeras. “Olahraga tidak akan membuatmu mati!”
“Kami di sini bukan kepengin dicetak jadi atlet. Jangan lampiasin obsesi Ibu yang gagal jadi atlet itu ke kami, dong!” timpal Bayu sembari mengangkat kedua tangannya.
Bukan hal mengejutkan jika Bayu mengetahui kegagalan Bu Rina menjadi atlet basket putri. Rumor itu sudah beredar dari tahun ke tahun sejak pertama kali Bu Rina mengajar di SMA Ibu Bangsa.
Muka Bu Rina memerah, telunjuknya terarah ke muka Bayu. “Jangan sekali-kali kamu mengungkit soal itu lagi! Kalau memang kamu tidak suka, kamu tidak usah masuk palajaran saya!” ucap Bu Rina dengan suara bergetar oleh emosi.
Bayu mengangkat kedua bahu dengan gaya tak acuh. Lelaki itu melemparkan senyum mengejek sebelum berjalan santai ke luar lapangan. Sementara semua siswa, termasuk Isvara, menahan napas tegang.
Bu Rina mengalihkan tatapannya dari Bayu kepada Isvara sehingga gadis itu terlonjak kaget. “Kenapa diam? Ayo terus lari! Dasar gendut lamban! Kamu selalu menghambat yang lain. Kamu tidak lihat yang lain jadi nungguin kamu sejak tadi?” Bu Rina kemudian melemparkan bola basket sekencangnya hingga membentur tiang bendera dan menimbulkan gedebuk keras.
Mendengar hinaan itu, spontan Isvara menyeret kakinya untuk berlari. Tiap langkah terasa lebih berat daripada sebelumnya. Degup jantung Isvara berpacu cepat seiring matanya yang memanas. Kata ‘gendut’ dan ‘lamban’ terus terngiang-ngiang di kepalanya. Membuatnya jijik kepada diri sendiri.